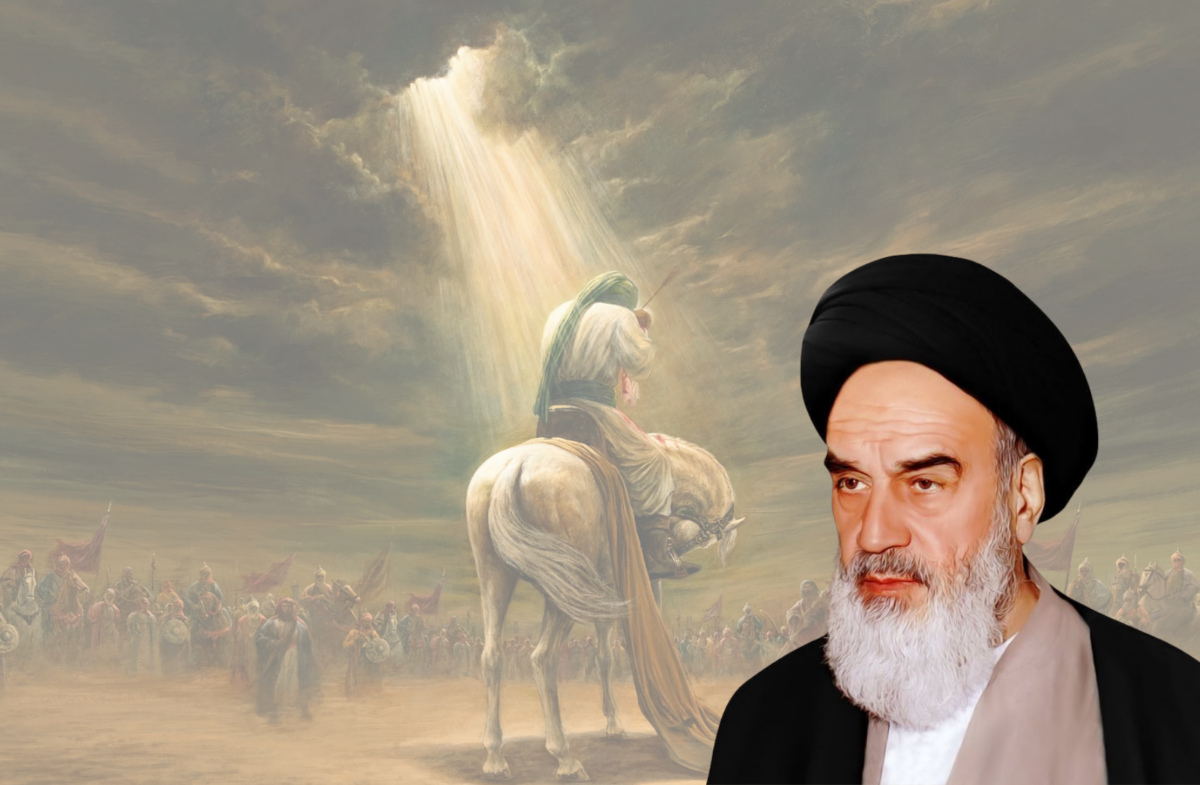Sejarah Islam mencatat banyak peristiwa besar, tetapi tidak ada yang memiliki resonansi spiritual dan moral yang setara dengan tragedi Karbala. Di padang tandus itu, pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, cucu Nabi Muhammad saw, Imam Husain bin Ali as, berdiri tegak menghadapi kekuasaan tiranik Yazid bin Muawiyah. Bukan karena ambisi dunia, tetapi karena panggilan jiwa dan amanah sejarah. Dalam langkahnya menuju Karbala, Imam Husain menghidupkan kembali semangat Islam awal—Islam yang berakar pada keadilan, ketakwaan, dan kebebasan dari belenggu penguasa zalim.
Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Murtadha Muthahhari, tragedi ini bukanlah titik lahir dari mazhab Syiah, melainkan puncak dari proses pemisahan spiritual dan intelektual antara dua pendekatan berbeda dalam memahami Islam. Dalam bukunya Ashura: Roots, Motives, and Lessons, Muthahhari menegaskan bahwa Syiah adalah hasil dari kesadaran Islam yang tidak mau berkompromi terhadap kebatilan, bahkan ketika kebatilan itu memakai jubah keagamaan dan kekhalifahan.
Islam yang Terpecah oleh Kekuasaan, Bukan oleh Keyakinan
Sebelum tragedi Karbala, umat Islam hidup dalam dinamika perbedaan pendapat yang masih bisa didekati dengan semangat ukhuwah. Setelah wafatnya Rasulullah, terjadi perdebatan mengenai siapa yang paling berhak melanjutkan kepemimpinan umat. Bagi kalangan yang kelak disebut sebagai Syiah, keimaman adalah kelanjutan spiritual dari kenabian—bukan dari sisi wahyu, tetapi dari sisi penjagaan agama. Imam bukan hanya pemimpin administratif, tapi juga penjaga nilai, penafsir Al-Qur’an, dan teladan akhlak.
Namun, Syiah tidak tumbuh dalam ruang kosong. Ia bertumbuh dari luka sejarah, dari ketidakadilan yang dirasakan oleh banyak umat Islam ketika kekuasaan mulai dijadikan warisan dinasti, bukan amanah Ilahi. Di sinilah, sebagaimana disampaikan oleh Muthahhari, Syiah menampilkan perlawanan bukan terhadap Sunni, tetapi terhadap Islam yang telah kehilangan ruhnya di tangan para penguasa yang mengkhianati nilai-nilai Rasulullah.
Karbala menjadi refleksi konkret dari konflik antara Islam moral dan Islam politik. Yazid mewakili bentuk kekuasaan yang ingin menundukkan agama di bawah kaki kepentingan. Sedangkan Imam Husain tampil sebagai simbol Islam yang menolak tunduk, meski harus ditebus dengan nyawa.
Karbala Bukan Awal, Tapi Puncak
Banyak yang mengira Syiah lahir dari peristiwa Karbala. Padahal, sebagaimana disebut dalam pelbagai riwayat dan analisis sejarah, gagasan Imamah sudah tertanam sejak masa Rasulullah. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang Ulil Amri, Tathir, dan peristiwa Ghadir Khum menjadi dasar spiritual dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Namun, selama beberapa dekade pasca-Rasulullah, Syiah masih belum menjadi entitas sosial yang terpisah. Ia lebih sebagai kecenderungan cinta dan loyalitas terhadap Ahlul Bait.
Peristiwa Karbala mengubah itu semua. Setelah darah suci Imam Husain tertumpah, umat mulai menyadari bahwa ada dua jalan yang sangat berbeda: satu jalan yang mengikuti jejak kekuasaan dinasti, dan satu jalan yang setia kepada nilai-nilai kenabian. Di sinilah lahir identitas Syiah secara historis: bukan dari kebencian terhadap sahabat atau umat, tetapi dari peneguhan terhadap kebenaran yang diwariskan Nabi.
Sebagaimana dikisahkan dalam Futuh al-Buldan, Imam Husain berkata, “Wahai manusia! Inilah aku, putra dari putri Nabi. Kami lebih layak memimpin kalian daripada orang-orang yang mengklaim hak itu tanpa dasar” (Futuh al-Buldan, vol. V, hal. 144–145).
Rekonsiliasi dalam Pandangan Kemanusiaan
Satu hal yang sangat penting untuk digarisbawahi adalah bahwa Karbala bukan tragedi milik Syiah semata. Ia adalah luka kolektif umat Islam. Tak sedikit ulama Ahlusunah yang mencintai Husain dan mengutuk pembunuhannya. Dalam Tarikh Thabari, banyak disebutkan tokoh-tokoh dari Kufah, Basrah, dan Madinah yang menangisi tragedi Karbala dan merasa berdosa karena diam.
Bahkan dalam sastra Sunni, seperti dalam karya-karya Imam Ghazali atau Jalaluddin Rumi, nama Husain disanjung tinggi. Ini membuktikan bahwa cinta kepada Ahlulbait tidak pernah menjadi milik eksklusif Syiah. Karbala adalah milik nurani setiap Muslim yang mencintai keadilan, mencintai Nabi, dan ingin Islam yang murni kembali ditegakkan.
Oleh karena itu, ketika kita mengenang Karbala hari ini, kita tidak sedang menghidupkan perpecahan lama. Justru sebaliknya, kita mengingatkan kembali bahwa umat Islam harus bersatu dalam semangat Husain: menolak tirani, menegakkan keadilan, dan tidak membiarkan agama dijadikan alat legitimasi penguasa zalim.
Karbala Adalah Cermin
Murtadha Muthahhari menulis bahwa peristiwa Asyura ibarat cermin bagi umat. Di dalamnya, kita melihat diri kita sendiri: apakah kita berdiri di sisi Husain atau di sisi kekuasaan? Apakah kita memilih untuk diam demi kenyamanan, atau berani bersuara demi kebenaran?
Para syuhada Karbala bukanlah sekelompok ekstremis atau pemberontak, melainkan manusia-manusia yang menjadikan nilai-nilai ilahi sebagai pusat hidup mereka. Seperti yang ditulis oleh Muslim bin Ziyad: “Demi Allah, Muawiyah tidak berhak menjadi khalifah. Ia merampas hak penerus Nabi dengan tipu daya.” (Futuh al-Buldan, vol. V, hal. 194)
Demikian pula Hilal bin Nafi’ menulis: “Aku percaya kepada agama Husain dan ayahnya, Ali.” (Futuh al-Buldan, vol. V, hal. 201) Ini bukan sekadar pernyataan kesetiaan, tapi pengakuan ideologis terhadap Islam yang hakiki.
Penutup: Menyatukan Hati dalam Nama Imam Husain
Karbala bukan untuk ditangisi semata, tapi untuk dijadikan lentera dalam menempuh jalan yang benar. Ia bukan untuk menuding siapa yang benar dan siapa yang sesat, melainkan untuk merenung bersama, bagaimana kita bisa menjadi umat yang lebih adil, lebih berani, dan lebih tulus dalam mengikuti ajaran Rasulullah saw.
Di atas padang Karbala, Imam Husain berkata:
“Jika agama Muhammad hanya akan tegak dengan darahku, maka ambillah nyawaku, wahai pedang-pedang!” Ini bukan seruan sektarian, melainkan suara ilahi dari seorang cucu Nabi yang mewakili seluruh umat.
Hari ini, mengenang Karbala berarti kembali kepada jati diri Islam. Bukan Islam yang dipisahkan oleh mazhab, tetapi Islam yang menyatukan hati dalam nilai-nilai keadilan, keberanian, dan cinta kepada Ahlulbait.
Referensi:
- Murtadha Muthahhari, Ashura: Roots, Motives, and Lessons
- Rasul Jafariyan, Sejarah Para Pemimpin Islam