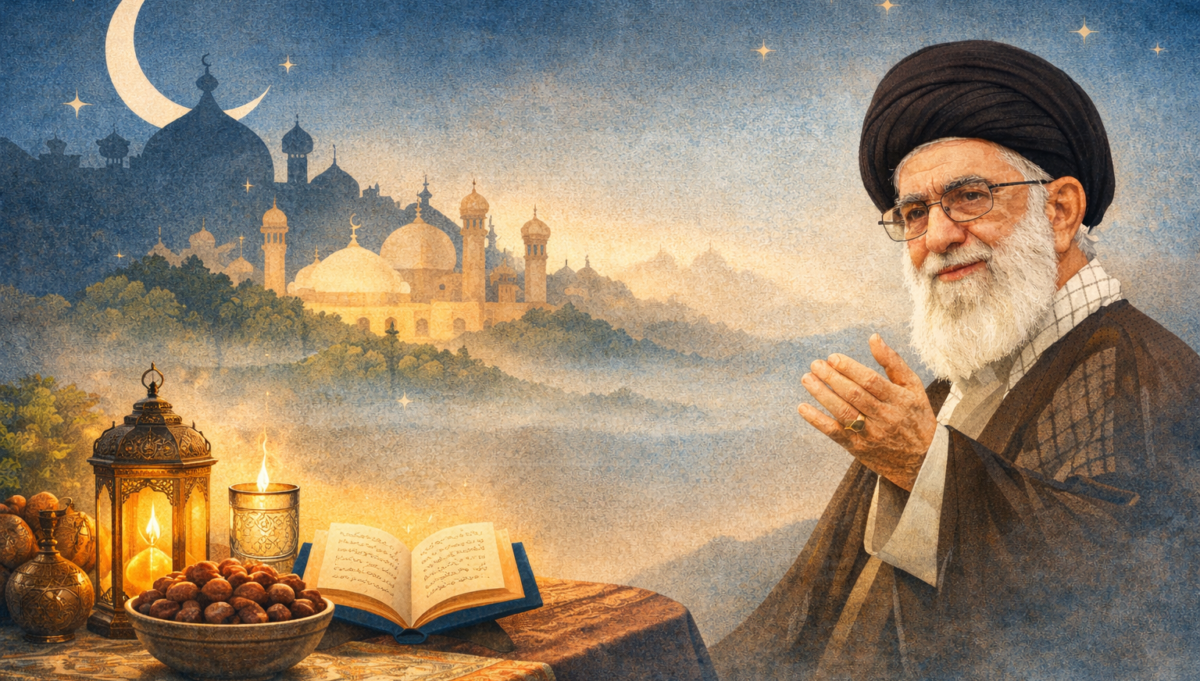Dalam pandangan Islam, nilai sejati manusia tidak diukur dari apa yang tampak di mata dunia: kekuasaan, harta, atau keturunan. Tolok ukur itu diukur dari pilihan moral dan spiritual yang dibuat seseorang ketika berhadapan dengan dua jalan yang bertentangan—antara hawa nafsu dan ketaatan, antara kesenangan duniawi dan ridha Ilahi. Al-Qur’an dengan penuh penegasan memuji manusia-manusia yang memilih jalan benar di antara dua kemungkinan itu, setelah mereka menundukkan keinginan yang menggoda dan menahan diri dari hidup bermewah-mewah.
Ujian Nilai di Hadapan Godaan
Salah satu kisah yang menggambarkan makna sejati nilai spiritual adalah kisah Nabi Yusuf as. Beliau masih muda dan rupawan, dan diuji dengan godaan dari Zulaikha, seorang wanita berkuasa dan cantik yang berusaha menundukkannya. Pintu-pintu terkunci, situasi menjerumuskan, dan tak ada mata manusia yang melihat. Namun Yusuf memilih Allah di atas segalanya. Ia berkata, “Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguh, orang-orang yang zalim tidak akan beruntung.” (QS. Yusuf: 23)
Dari kisah ini tampak bahwa nilai manusia tidak terletak pada seberapa besar ia mampu mencapai sesuatu, tetapi seberapa teguh ia menolak yang dilarang meski punya peluang untuk melakukannya. Ketika pilihan dunia terbuka lebar, tetapi seseorang memilih untuk menundukkan diri pada Allah, di situlah nilai sejatinya diuji.
Ibrahim dan Puncak Pengorbanan
Begitu pula dengan Nabi Ibrahim as. Setelah sekian lama menanti kehadiran seorang anak, Allah mengaruniakannya Ismail. Namun tak lama kemudian, datanglah perintah Ilahi: “Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu di jalan Allah.” Di sinilah dua cinta bertemu dan bertarung dalam diri seorang manusia: cinta seorang ayah terhadap anaknya, dan cinta hamba kepada Tuhannya.
Ibrahim memilih ketaatan. Ia memanggil Ismail dan berkata, “Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu?” Ismail menjawab dengan kepasrahan yang luar biasa: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.” (QS. As-Shaffat: 102–105)
Di sinilah nilai seorang manusia mencapai puncaknya—bukan pada kebesaran lahir, tetapi pada keikhlasan dalam pengorbanan.
Pengorbanan Ahlulbait: Cermin Cinta dan Nilai
Keteladanan juga datang dari Ahlulbait Nabi. Dikisahkan bahwa Imam Ali as dan Sayyidah Fatimah az-Zahra as, bersama Hasan dan Husain, berpuasa beberapa hari. Namun setiap kali waktu berbuka tiba, mereka hanya minum air putih, sedangkan makanan mereka diberikan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.
Al-Qur’an mengabadikan peristiwa itu dalam firman-Nya:
“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.” (QS. Al-Insan: 8)
Bagi mereka, lapar bukan sekadar ujian jasmani, tetapi latihan batin untuk menundukkan ego. Dalam diri Ahlulbait, nilai manusia tampil dalam bentuk kasih, empati, dan kesediaan berkorban.
Al-Qur’an juga memuji mereka yang menghidupkan malamnya dengan doa dan munajat. “Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap.” (QS. As-Sajdah: 16). Mereka bukan hanya beriman, tetapi mengekspresikan keimanannya dengan tindakan yang konkret, dengan meninggalkan kesenangan tidur demi mencari cahaya Allah.
Kebebasan dalam Memilih: Hakikat Nilai
Maka, tolok ukur nilai manusia di sisi Allah terletak pada kebebasannya dalam memilih jalan yang benar meski digoda oleh dunia dan dorongan nafsu. Nilai sejati muncul saat manusia mengalahkan dirinya sendiri. Ia tetap diam walau mampu berbicara tajam, ia menahan amarah walau mampu membalas. Inilah kekuatan moral yang membuat manusia bernilai.
Namun muncul pertanyaan: jika di dunia setiap amal langsung dibalas, bukankah manusia akan menjadi saleh karena takut, bukan karena kesadaran? Jawabannya: benar. Karena surga dan neraka tidak tampak di depan mata, manusia dibiarkan memilih dengan bebas, tanpa tekanan. Itulah sebabnya Allah menunda ganjaran dan hukuman hingga waktu yang telah ditentukan—agar kebaikan lahir dari kesadaran, bukan ketakutan.
Mengapa Balasan Tidak Diberikan di Dunia
Dunia ini bukan tempat balasan yang sempurna. Tidak mungkin pahala dan hukuman diukur di dunia yang fana. Bagaimana mungkin balasan bagi Rasulullah saw. yang membebaskan manusia dari kegelapan hanya berupa kenikmatan duniawi seperti makanan atau kemewahan? Bukankah pelaku dosa juga dapat menikmati hal yang sama?
Atau, bagaimana mungkin hukuman bagi seorang pembantai ratusan ribu jiwa cukup dengan satu kali hukuman mati? Di sinilah letak rahasia besar keadilan Ilahi. Dunia hanyalah tempat ujian, sedangkan Hari Kebangkitan adalah tempat keadilan ditegakkan sepenuhnya.
Allah berfirman: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Dia merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS. Ar-Rum: 41)
Maka, penderitaan dan bencana dunia hanyalah peringatan kecil dari azab yang lebih besar di akhirat. Di dunia, Allah menegur manusia agar sadar; di akhirat, Dia menegakkan keadilan tanpa kompromi.
Hikmah Penundaan Hukuman
Al-Qur’an menegaskan: “Jika Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang ditentukan.” (QS. An-Nahl: 61).
Penundaan hukuman ini bukan karena kelalaian, tetapi karena rahmat. Sebab, manusia diberi kesempatan untuk bertobat. Banyak orang yang dulunya bergelimang dosa, namun di akhir hayatnya bertaubat tulus dan berubah total.
Contoh paling indah adalah Al-Hurr, salah satu komandan pasukan musuh di Karbala. Di tengah medan perang, nuraninya tersentak oleh kebenaran Imam Husain as. Ia berbalik arah, meninggalkan barisan Yazid, dan gugur sebagai syuhada di sisi Imam Husain. Jika Allah menghukumnya saat itu juga, bagaimana mungkin ia mendapat kesempatan untuk menebus dosanya?
Inilah rahmat Allah yang meliputi seluruh makhluk-Nya.
Keadilan dalam Akibat Perbuatan
Allah berfirman: “Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan akibat-akibat yang mereka tinggalkan.” (QS. Yasin: 12).
Setiap amal, baik atau buruk, meninggalkan jejak yang terus hidup setelah pelakunya tiada. Seorang yang menanam kebaikan akan terus menerima pahala dari setiap orang yang meneladaninya. Sebaliknya, orang yang menabur keburukan akan terus menanggung dosa selama akibat perbuatannya masih berlangsung. Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa memulai suatu amalan baik, maka ia mendapat pahala dari amal itu dan dari orang-orang yang mengikutinya. Barang siapa memulai suatu kejahatan, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang menirunya.” (Safinatul Bihar, jilid II, hal. 261)
Mengapa Harus Ada Hari Pembalasan
Keadilan Ilahi menuntut adanya tempat dan waktu bagi pembalasan yang sempurna. Jika dunia ini hanya diakhiri dengan kematian, maka tidak ada keadilan bagi orang-orang saleh yang menderita, dan tidak ada ganjaran bagi para penindas yang hidup dalam kemewahan. Karena itu, logika keadilan meniscayakan adanya Hari Kebangkitan.
Al-Qur’an berkali-kali menantang akal manusia:
“Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Patutkah Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?” (QS. Shad: 28)
“Maka apakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama.” (QS. As-Sajdah: 18).
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan kata, tetapi untuk menggugah hati. Dunia ini memang tidak selalu adil, tetapi keadilan Allah pasti datang.
Kesimpulan: Nilai Manusia dan Keadilan Ilahi
Dari semua uraian di atas, jelaslah bahwa ukuran nilai manusia dalam Islam adalah sejauh mana ia memilih jalan yang benar di tengah godaan, sejauh mana ia berani mengorbankan yang dicintai demi ridha Allah, dan sejauh mana ia bertahan dalam ketaatan ketika dunia menawarkan kesenangan.
Manusia dinilai bukan dari hasil akhirnya, melainkan dari proses pilihan moral yang diambilnya. Karena itu, Allah tidak segera menghukum atau memberi ganjaran di dunia—agar setiap manusia memiliki kesempatan untuk menyadari, bertobat, dan memperbaiki diri.
Keadilan Allah bukan sekadar memberi pahala dan hukuman, tetapi juga memberi waktu, memberi peluang, memberi harapan. Sebab tanpa kebebasan dan kesempatan, tidak ada makna nilai.
Hari Kebangkitan adalah hari penegakan nilai itu sendiri: hari ketika setiap kebaikan dan keburukan mencapai akibatnya, dan setiap jiwa berdiri di hadapan Tuhannya, tanpa tirai, tanpa alasan, tanpa penundaan lagi.
Maka, selama napas masih ada, selama waktu masih diberikan, tugas manusia hanyalah satu: memilih dengan sadar. Sebab setiap pilihan akan menulis nilai kita sendiri di lembar catatan Ilahi—lembar yang akan dibuka di hadapan kita, pada hari ketika segala kebenaran terungkap dan segala rahasia dibalas dengan sempurna.
Disadur dari buku karya Ayatullah Mukḥsin Qara’ati – Misteri Hari Pembalasan: Dalil Al-Qur’an dan Argumen Akal