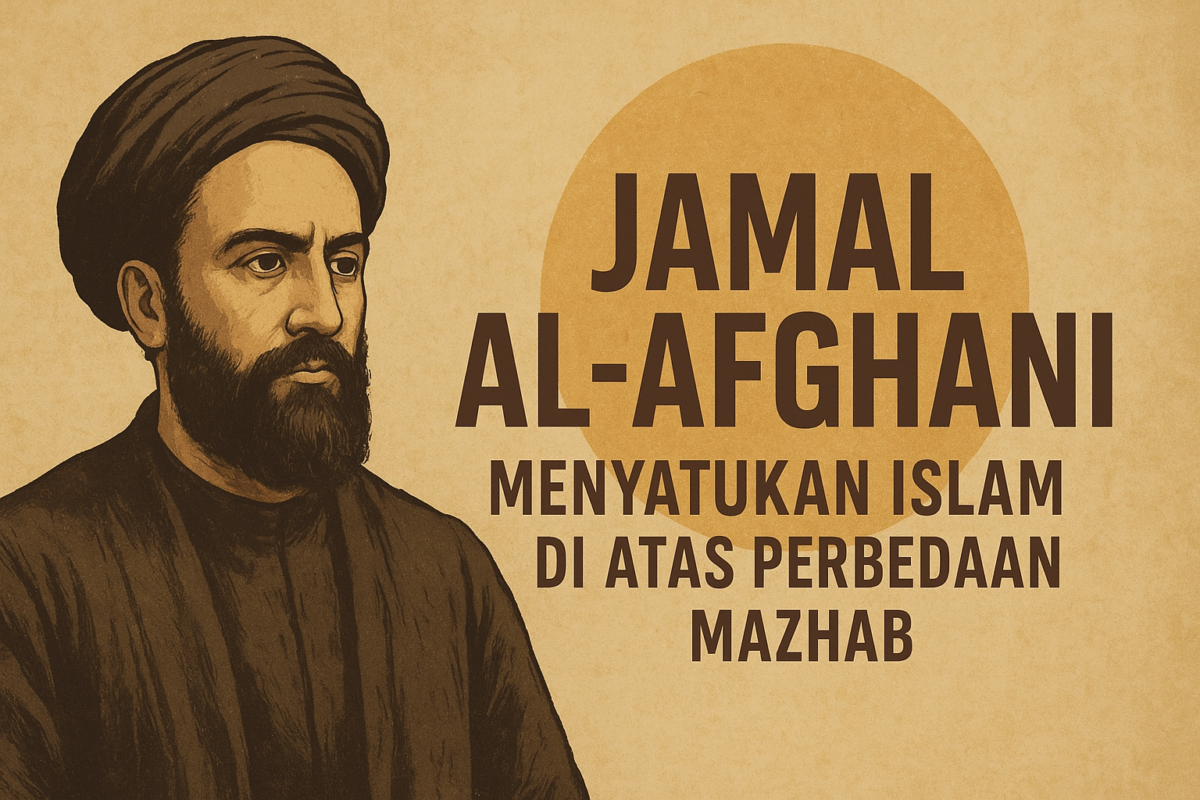Dalam lembar-lembar sejarah Islam, tidak banyak tokoh yang meninggalkan jejak sekuat Sayidah Fatimah al-Zahra as. Ia adalah perempuan suci yang tidak hanya hidup sebagai putri Rasulullah, tetapi sebagai penjaga ruh Islam di masa ketika arus sejarah mulai menggeser nilai-nilai yang ditegakkan ayahnya. Dalam pandangan Murtadha Muthahhari—filsuf dan pemikir revolusioner Iran—hari-hari terakhir Fatimah adalah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah Islam. Itulah masa ketika seorang perempuan berdiri tegak menantang penyimpangan politik, sementara mayoritas umat memilih diam.
Melalui karya-karyanya seperti “The Life and Character of Fatima Zahra” dan “Imamate and Leadership”, Muthahhari memandang perjuangan Fatimah bukan sekadar isu keluarga Nabi, tetapi perang moral untuk mempertahankan otentisitas Islam. Dalam kacamata beliau, Fatimah bukan tragedi, tetapi kesadaran—kesadaran yang menyelamatkan umat dari distorsi yang bisa mengubah wajah Islam untuk selamanya.
Ketika Rumah Nabi Menjadi Pusat Gejolak Sejarah
Setelah wafatnya Rasulullah saw, umat Islam memasuki masa penuh ketegangan politik. Muthahhari menegaskan bahwa perubahan itu berlangsung sangat cepat: nilai-nilai dakwah yang dibangun bertahun-tahun berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang berbalut jargon persatuan. Dalam situasi genting inilah, Fatimah tampil bukan sebagai perempuan yang larut dalam duka ayah, melainkan sebagai sosok yang memahami sepenuhnya konsekuensi sejarah dari setiap penyimpangan yang terjadi.
Menurut Muthahhari: “Fatimahlah yang paling memahami apa yang sedang hilang. Ia berdiri bukan karena duka, tetapi karena pandangan yang jernih.”
Fatimah melihat bahwa umat sedang berjalan menuju jurang. Ia tahu bahwa diam pada saat itu berarti membuka pintu panjang bagi penindasan Ahlulbait, yang kelak berpuncak pada tragedi Karbala. Karena itulah, ia tidak memilih diam. Ia bergerak. Ia berbicara. Ia memperingatkan.
Pidato-pidato yang Menghidupkan Nurani Umat
Muthahhari memberikan perhatian besar pada Khutbah Fadakiyah, pidato agung yang disampaikan Sayidah Fatimah di Masjid Nabawi. Dalam pidato itu, Sayidah Fatimah menampilkan kapasitas luar biasa sebagai seorang pemikir, ahli fiqih, dan penjaga kesadaran sosial. Ia memulai pidatonya dengan ayat-ayat Al-Qur’an, lalu membangun argumentasi politik dan teologis yang sangat kuat.
Menurut Muthahhari, pidato itu tidak dimaksudkan untuk memulihkan hak pribadi—karena Fatimah adalah simbol kerelaan dan kesederhanaan. Pidato itu adalah peringatan politik terbuka bahwa arah pemerintahan telah berbelok dari prinsip-prinsip Nabi.
Sayidah Fatimah menjelaskan:
- posisi Ahlulbait sebagai pewaris risalah,
- kewajiban umat menjaga amanat Nabi di Ghadir,
- bahaya kekuasaan tanpa legitimasi Ilahi,
- dan pentingnya keadilan sebagai fondasi kepemimpinan.
Muthahhari menulis: “Pidatonya bukanlah keluhan tentang harta. Itu adalah manifesto keadilan.”
Dengan kata lain, pidato itu adalah deklarasi ideologis. Ia menempatkan kembali Ahlulbait sebagai pusat otoritas agama, bukan dekorasi sejarah.
Fadak: Simbol Kebenaran, Bukan Sengketa Tanah
Kasus Fadak adalah titik penting dalam perjuangan Sayidah Fatimah. Muthahhari meluruskan pandangan bahwa Fadak hanyalah perkara warisan. Ia menjelaskan bahwa Fatimah memperjuangkan Fadak bukan untuk dirinya, tetapi sebagai ujian apakah umat masih memegang sabda Nabi.
Fadak—sebuah lahan produktif yang diberikan Rasulullah kepada Fatimah berdasarkan ayat Al-Qur’an (QS. al-Hashr: 7)—dijadikan simbol legitimasi. Bila sabda Nabi tentang Fadak ditolak, maka umat sedang membuka jalan untuk menolak sabda-sabda lainnya, termasuk sabda tentang kepemimpinan Imam Ali.
Muthahhari menjelaskan: “Sayidah Fatimah memperjuangkan Fadak untuk melindungi tradisi kenabian, bukan untuk memperoleh tanah. Fadak adalah perisai kebenaran.”
Karena itu, perjuangan Sayidah Fatimah soal Fadak adalah perjuangan menjaga integritas risalah, bukan sengketa ekonomi.
Luka di Pintu Rumah: Ketika Seorang Suci Dibalas Kekerasan
Muthahhari tidak menghindari fakta tragis bahwa Sayidah Fatimah mengalami kekerasan fisik ketika rumah Imam Ali dikepung oleh sekelompok orang yang ingin memaksa baiat. Ia menegaskan bahwa peristiwa itu bukan sekadar insiden politik, tetapi menunjukkan bahwa kekuasaan saat itu mulai menjauhi nilai-nilai moral Islam.
Luka-luka yang menimpa Sayidah Fatimah bukan hanya melukai tubuh seorang perempuan suci, tetapi melukai akal umat. Muthahhari menekankan bahwa umat harus belajar dari tragedi ini bahwa kekuasaan tanpa legitimasi moral cenderung berubah menjadi tirani.
Dalam tulisannya, ia menegaskan: “Penindasan terhadap Sayidah Fatimah adalah penindasan terhadap kebenaran itu sendiri.”
Luka itu menjadi cahaya sejarah. Ia bukan mematahkan Sayidah Fatimah—ia justru mengukuhkan keteguhannya.
Wasiat Terakhir: Diam yang Lebih Keras dari Pidato
Sikap paling mengguncang dari Fatimah adalah wasiat pemakaman malam harinya. Ia meminta agar beberapa tokoh yang telah menzaliminya tidak menghadiri pemakamannya. Dalam perspektif Muthahhari, keputusan ini adalah bentuk protes politik paling keras dalam sejarah Islam.
Fatimah memilih sunyi agar generasi selanjutnya bertanya: Mengapa putri Nabi dimakamkan secara rahasia? Mengapa ia tidak merelakan kehadiran sebagian penguasa?
Muthahhari menulis: “Pemakaman sunyinya adalah sebuah vonis. Lebih dahsyat daripada pidato apa pun.”
Pemakaman senyap itu adalah dokumen sejarah yang tidak bisa dihapus oleh siapa pun. Ia menjadi tanda bahwa sesuatu yang sangat besar dan sangat kelam telah terjadi setelah wafatnya Nabi.
Fatimah dan Garis Keadilan: Warisan bagi Umat Penentang Kezaliman
Dalam pemikiran Muthahhari, perjuangan Fatimah bukanlah peristiwa yang berakhir pada zamannya. Perjuangan itu menjadi “benih kesadaran” yang kelak tumbuh dan meledak dalam sejarah, terutama di Karbala. Dari Sayidah Fatimah, lahirlah al-Husein. Dari luka Fatimah, tercipta barisan para penentang tirani sepanjang masa.
Karena itu, Muthahhari melihat Sayidah Fatimah sebagai:
- pelopor kesadaran politik Islam,
- simbol perempuan revolusioner,
- penjaga moralitas umat,
- dan teladan bagi generasi yang ingin melawan kezaliman.
Ia menegaskan:
“Tanpa ketegasan Sayidah Fatimah, Islam akan kehilangan kompas moralnya.”
Fatimah telah menanamkan prinsip bahwa kebenaran harus dipertahankan, meski dunia tidak mendengar.
Fatimah, Cahaya yang Tidak Pernah Padam
Hari-hari terakhir Fatimah bukan sekadar periode duka keluarga Nabi. Dalam pandangan Muthahhari, itulah saat ketika seorang perempuan berdiri untuk menyelamatkan risalah. Ia berdiri ketika para sahabat besar diam. Ia berbicara ketika politik menutupi kebenaran. Ia memilih luka daripada kompromi. Ia memilih maqam abadi daripada kenyamanan sesaat.
Fatimah pergi dalam keadaan terzalimi, tetapi kezaliman itu justru menjadikan suaranya abadi. Dan dalam kata-kata Muthahhari, Fatimah adalah perempuan yang tidak mati; ia hadir dalam setiap perjuangan menegakkan keadilan.
Referensi Karya Murtadha Muthahhari
- Murtadha Muthahhari, The Life and Character of Fatima Zahra
- Murtadha Muthahhari, Imamate and Leadership
- Murtadha Muthahhari, Fundamentals of Islamic Thought