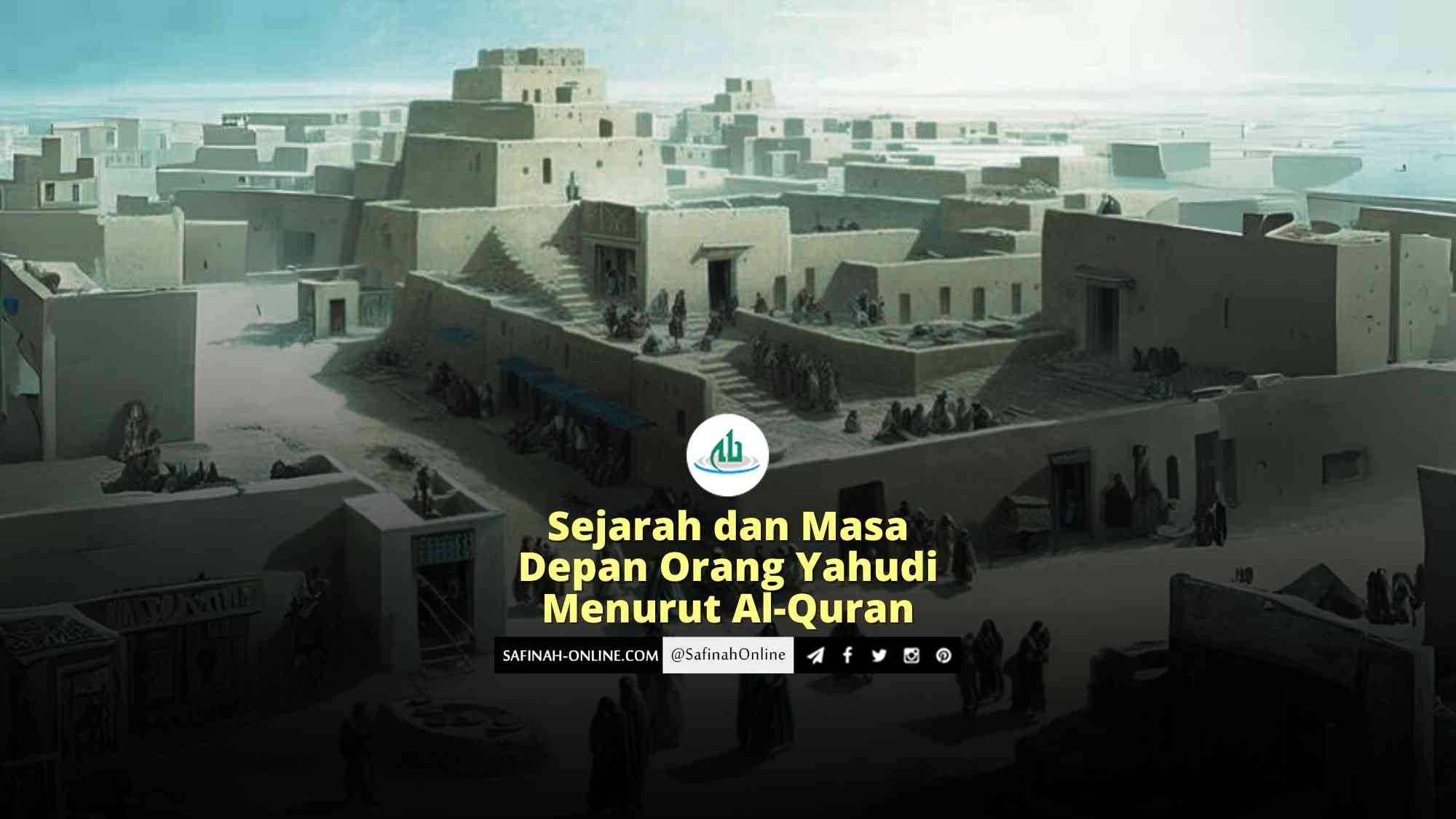Komunitas Islam di tahun terjadinya peristiwa Karbala sangat berbeda dengan tahun-tahun terakhir kehidupan Nabi. Kecenderungan penyimpangan telah meningkat secara gradual. Menurut para peneliti, basis penyimpangan itu terbentuk sejak tahun pertama wafatnya Nabi. Penyimpangan yang terus berlanjut, berkembang sedemikian rupa sehingga para politisi bisa menangguk keuntungan dari kondisi tersebut.
Mereka bukan hanya menipu penduduk, tetapi juga menjustifikasi tirani yang mereka lakukan. Orang-orang yang memainkan peran penting dalam memulai dan mengembangkan penyimpangan semacam itu adalah para Bani Umayah. Dalam pemerintahan yang dikuasai oleh Yazid, terungkap fakta bahwa Bani Umayah sama sekali tidak percaya pada Islam yang sejati. Keyakinan mereka semata-mata merupakan selubung yang ditebarkan untuk menjustifikasi dan membuat kekuasaan mereka diterima.
Imam Husain as mengatakan bahwa Bani Umayah adalah orang-orang yang taat kepada setan, ingkar kepada Allah, dan menyebarkan perbuatan dosa. Mereka juga mengabaikan ketentuan Allah yang sudah pasti dan melanggar hak Baitul Mal (Ansab al-Asyraf, 3/171). Selain itu, mereka telah membuat kerusakan dan mengabaikan batas-batas yang ditetapkan Tuhan, serta merusak sejumlah besar konsep agama dan menyalahgunakannya.
Baca: Pemberontakan Penduduk Madinah Terhadap Pemerintahan Yazid Pasca Tragedi Karbala
Sekarang mari kita bahas beberapa konsep agama yang salah sehingga mendatangkan dampak bagi peristiwa Karbala berdasarkan bukti-bukti sejarah.
- Ketaatan kepada para imam
- Wajibnya ‘Jamaah’
- Haramnya melanggar sumpah
Ketiganya adalah istilah-istilah politis yang lazim digunakan oleh para penguasa. Meskipun demikian, tiga istilah ini sebenarnya merupakan prinsip yang benar dalam konsep agama, politik, dan konsep-konsep Islami demi kepentingan masyarakat, namun didistorsi tafsirnya oleh penguasa.
Taat kepada imam berarti taat kepada sistem pemerintahan yang ada. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana seorang penguasa harus ditaati. Apakah seorang imam yang adil harus diikuti dan seorang raja yang zalim juga harus ditaati?
Menjunjung tinggi “Jamaah” mengisyaratkan pentingnya menghindari kekacauan atau tidak bertindak apa pun yang bisa melemahkan persatuan atau membuka jalan bagi munculnya keterguncangan dalam komunitas Islam. Namun, pertanyaan yang harus diperhitungkan adalah apakah tindakan berdiam diri juga harus dilakukan dalam kondisi apa pun, terutama di hadapan monarkisme yang tiran dan penguasa yang zalim. Dengan kata lain, apakah segala macam keberatan harus ditekan dengan alasan bahwa hal itu bisa merusak “Jamaah” dan “menyebabkan perpecahan”?
Haramnya melanggar sumpah setia, yaitu melanggar sebuah sumpah ditekankan dengan kuat dalam Islam. Karena melanggar janji atau sumpah setia itu begitu serius dilarang, maka hal itu tergantung pada sejauh mana peran urusan politis itu bernilai positif. Tetapi jika sumpah setia itu tidak diikrarkan kepada khalifah-khalifah seperti Yazid atau dilanggar, dan sebagai akibatnya “Jamaah” menjadi rusak, maka sekali lagi apakah hal itu bisa dinilai dengan prinsip haramnya melanggar sumpah setia, atau pada dasarnya bisa menjadi sebuah perkecualian?
Para khalifah Bani Umayah dan kemudian dari Bani Abbasiyah dengan memanipulasi konsep-konsep semacam itu, bagaimanapun rusak dan tidak terjaminnya, telah memaksa penduduk untuk menerima kedaulatan mereka. Setelah Muawiyah mengamankan sumpah setia bagi putranya, Yazid, dia pergi ke Madinah guna memaksa lawan-lawannya untuk bersumpah.
Muawiyah pernah berkata kepada Aisyah, “Aku telah menjamin sumpah setia bagi Yazid dari semua umat Islam, jika kau mau. Tak pernah aku menyatakannya halal, tetapi sebaliknya bertindaklah moderat kepada penduduk.” (Futuh al-Buldan, 4/237, al-Imamah wa as-Siyasah, 1/183)
Mari kita perhatikan satu contoh lain. Ibnu Ishaq ketika melaksanakan salat (mungkin di Masjidil Haram), mereka melihat bahwa Syimr bin Dzil Jausyan ada di antara mereka. Dia mengangkat tangannya sambil berkata, “Ya Allah, Engkau tahu betul kemuliaanku, maka ampunilah daku.”
Berkata Ibnu Ishaq, “Bagaimana mungkin kau akan diampuni sedangkan kau telah membantu dan mendukung dalam pembunuhan putra Nabi?”
“Apa yang telah kami lakukan? Itu adalah perintah dari para komandan kami, dan dalam keadaan apa pun kami tak akan bisa menentang mereka. Jika tidak taat, kami akan menjadi jauh lebih rendah daripada binatang-binatang pengangkut air.”
Juga ketika Ibnu Ziyad menangkap Muslim bin Aqil berkata, “Wahai penjahat! Kau telah memisahkan diri dari imammu, dan telah menabur benih perpecahan di antara umat Islam.”
Muslim yang tak pernah melakukan penyimpangan seperti itu menjawab bahwa Muawiyah bukan hanya sama sekali tidak memperoleh khilafah melalui kesepakatan pendapat penduduk secara keseluruhan, tetapi juga melanggar hak penerus Nabi yang suci melalui penipuan dan menjarah khilafahnya.
Ketika Imam Husain hendak meninggalkan Mekah, utusan Amr bin Sa’id bin Ash, gubernur saat itu, berkata, “Tidakkah kau takut kepada Allah karena melepaskan diri dari ‘Jamaah umat Islam’ dan menyebabkan perpecahan di antara penduduk?”
“Kami tak pernah tidak taat kepada Imam, tidak pula kami memisahkan diri dari ‘Jamaah,'” tegas Amr bin Hajjaj, salah seorang komandan pasukan Ibnu Ziyad.
Sambil menasihati pasukan Ibnu Ziyad, dia menambahkan, “Jangan pernah berhenti mengingat ketaatan dan persatuan, dan kapan pun jangan pernah ragu membunuh orang yang memisahkan diri dari agama dan berseberangan dengan imam (penguasa).”
Figur-figur seperti Abdullah bin Umar membayangkan bahwa jika seluruh penduduk sepakat untuk bersumpah setia kepada Yazid, maka mereka juga akan sepakat. Dia telah menegaskan kepastiannya kepada Muawiyah, “Aku akan menentangmu kecuali semua penduduk bersumpah setia kepada putramu, Yazid.” Dia juga berkata kepada Imam Husain, “Jangan menyebabkan perpecahan di antara umat Islam!”
Orang-orang seperti putri Umar dan Abdurrahman bin Auf telah menulis surat kepada Imam agar menjadikan ketaatan kepada penguasa, menjaga “Jamaah” dan mengutamakannya sebagai hal yang mendesak.
Penyimpangan agama yang lain dalam komunitas Islam ini adalah “keyakinan pada fatalisme.” Sebelum peristiwa Karbala, keyakinan ini telah disalahgunakan. Namun demikian, di zaman awal Islam, Muawiyah telah menjadi orang yang menghidupkan kembali paham ini, bahkan menurut Abu Bilal Askari, dia adalah orang yang mengajarkannya pertama kali.
Baca: 40 Sahabat Imam Husain yang Gugur di Karbala
Merujuk pada fakta bahwa Muawiyah adalah pendiri “fatalisme”, Qadhi Abdul Jabbar mengutip bahwa Muawiyah telah menyampaikan sebuah pernyataan yang berharga, yaitu “Masalah yang berkenaan dengan Yazid merupakan takdir di antara takdir-takdir ketuhanan, dan tak seorang pun punya pilihan dalam hal ini.”Ubaidillah bin Ziyad bertanya kepada Imam Ali Sajjad as, “Bukankah Allah yang membunuh Ali Akbar?” Jawaban Imam adalah, “Aku mempunyai seorang kakak laki-laki yang dibunuh orang-orang.”
Ketika Umar bin Sa’d diprotes mengapa dia membunuh Imam Husain hanya demi mendapatkan pemerintahan kota Ray, dia menjawab bahwa kejadian seperti itu telah ditakdirkan.
Akibat-akibat penyimpangan seperti ini bagi generasi yang berikutnya adalah bahwa gerakan Imam Husain as. tidak pernah dianggap sebagai sebuah perlawanan terhadap pelanggaran moral, melainkan sebagai pemberontakan yang tidak sah.
*Disarikan dari buku Sejarah Para Pemimpin – Rasul Jakfarian