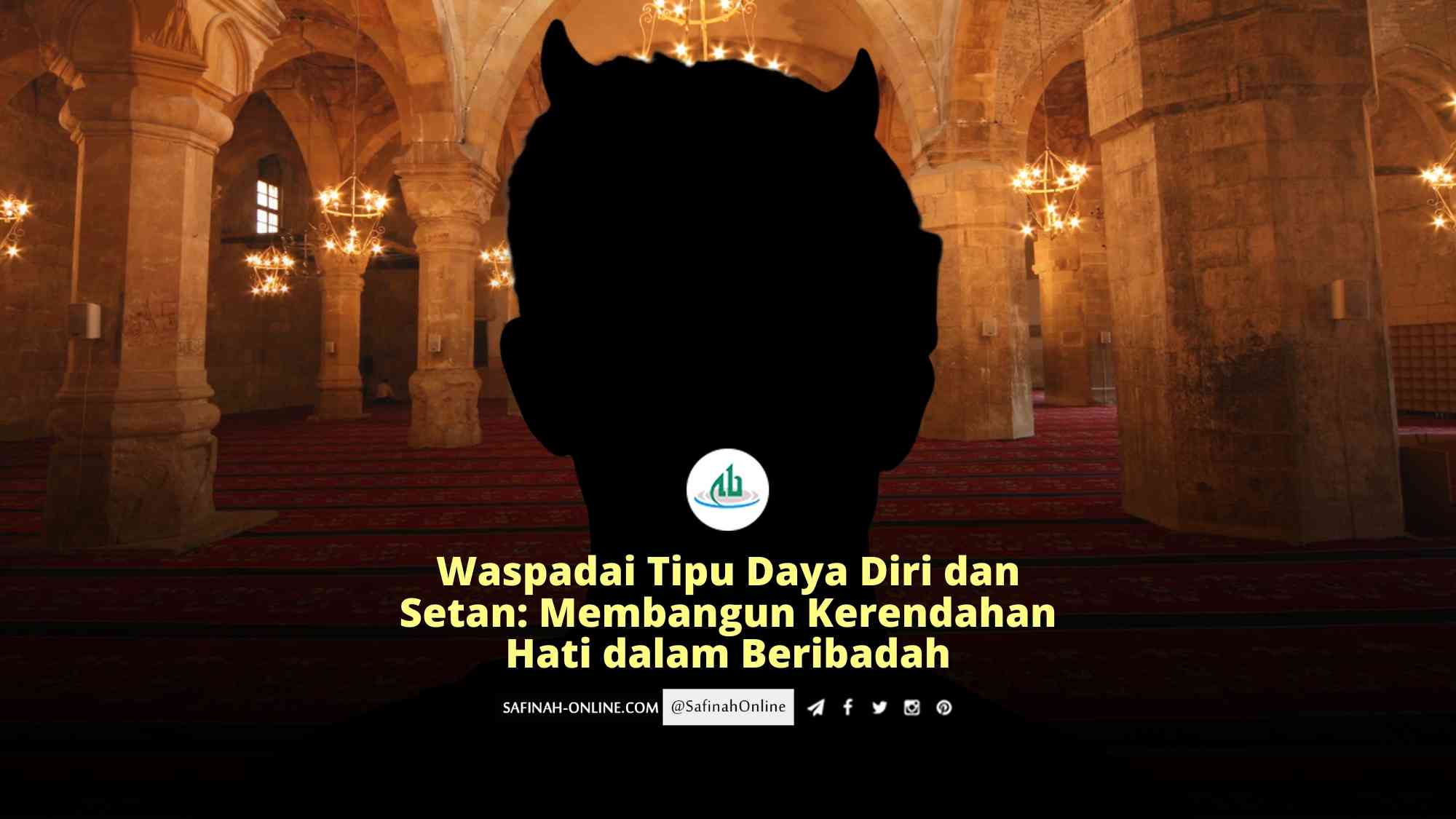Oleh: Dr. Muhsin Labib, MA
Salah satu musibah besar yang harus dihadapi umat manusia di abad modern adalah intoleransi. Sebagai musuh besar kemanusiaan, intoleransi merebak dalam banyak kasus di berbagai bidang kehidupan sosial bersama, khususnya dalam kehidupan antar dan intra agama.
Namun jika diamati lebih jauh, intoleransi antar agama tidak seintensif, atau setidaknya tidak sevulgar, intoleransi intra agama atau antar kelompok dalam agama yang sama. Ternyata, kebanyakan orang lebih mudah bersikap toleran terhadap pihak yang tidak seagama ketimbang dengan pihak yang seagama. Sebab, rivalitas terasa lebih sensitif dan intensif terjadi hanya karena berbeda pandangan dan aliran pemikiran. Apalagi jika sudah menyangkut ortodoksi.
Menariknya lagi, gejala intoleransi intra agama relatif bervariasi. Pada faktanya, tindak intoleransi berupa persekusi, misalnya, lebih kerap dilakukan terhadap kelompok muslim Syiah yang minoritas di suatu wilayah jika dibandingkan dengan kelompok minoritas yang dipercaya bukan hanya telah keluar dari pakem ortodoksi, bahkan telah menyimpang dari ajaran induknya (Islam), seperti Ahmadiyah dan Bahai (yang kuantitasnya lebih kecil lagi).
Intoleransi terhadap Syiah dilakukan secara intensif dalam dua skema:
1. Sosial
Intoleransi terhadap muslimin Syiah dalam skema sosial, biasanya berlangsung dalam dua modus.
a. Modus operasional yang cenderung sporadis, umumnya dengan mencatut umat Islam, muslimin Ahlussunnah, bahkan ormas atau aksi massa keagamaan tertentu serta ragam narasi dan ujaran provokatif figur-figur berpengaruh.
B. Modus institusional yang cenderung sistematis, melalui pembentukan organisasi dengan sasaran tunggal, yaitu membangun, melembagakan, dan mengawetkan kesalahapahaman hingga kebencian terhadap komunitas muslim Syiah.
Melalui modus kelembagaan (institusional) ini, intoleransi dimanipulasi sedemikian rupa agar di mata khalayak tampak sebagai “normal” dan legal, bahkan imperatif (sebagai bagian dari tugas “dakwah” yang harus dilakukan jika tak mau dianggap berdosa dan sesat). Intoleransi pun akan kehilangan (minimal, terselubungi) paras negatif, agresif, dan destruktifnya secara sosial. Objek dari intoleransi juga akan dianggap sah untuk dibenci, dipersekusi, hingga dieliminasi (kendati semua itu jelas-jelas melawan ideologi dan konstitusi negara).
Teknik intoleransi kelembagaan ini dimasifkan dengan:
1. Mengkampanyekan narasi setengah hati bahwa toleransi hanya berlaku antar agama. Di luar itu, termasuk intra agama, tidak berlaku toleransi lantaran standarnya bukan lagi “kerukunan hidup beragama” menurut intensi hukum dan undang-undang melainkan “kelurusan hidup beragama” menurut versi dan oknum tertentu.
2. Memfasilitasi penyesatan dan diskriminasi terhadap komunitas muslim Syiah, atau paling tidak, para elitnya membiarkan komunitasnya tanpa pembelaan atas hak kemanusiaan dan kenegaraannya sebagai salah satu elemen bangsa setiap kali terjadi aksi persekusi dan diskriminasi oleh massa dan otoritas.
3. Menuduh dan mencap secara eksplisit dalam forum khusus dan implisit dalam forum umum dengan stigma trans-nasional agar terus dicurigai sehingga kesulitan untuk berkembang dan melakukan konsolidasi.
Di sisi lain, upaya mengisolasi komunitas muslim Syiah juga dilakukan dengan menuduhnya sebagai ajaran transnasional. Seolah-olah ajaran keislaman Syiah tak punya akar dan jejak dalam sejarah Islam di Indonesia. Padahal sudah banyak dokumen dan monumen yang menunjukkan eksistensi ajaran, gagasan, dan komunitas Syiah di Indonesia sejak masa silam.
Dalam pergaulan modern sejak diciptakannya teknologi transportasi, yang dilanjutkan dengan pesatnya teknologi komunikasi di era pasca modern, di mana sekat-sekat geografis maupun demografis semakin mencair secara ekstrim, imajinasi tentang suatu entitas tunggal yang elemen-elemennya otentik dan organik pun ikut runtuh. Fakta ini, boleh dibilang, membuat semua “yang nasional” mau tak mau jadi “transnasional”.
Jelas sudah, cap sesat dan stempel transnasional bukan diumbar untuk dibuktikan benar salahnya. Tapi untuk menjadikan komunitas muslim Syiah yang jumlahnya tak lebih dari 1 juta jiwa ini sebagai target diskriminasi kultural oleh anasir ortodoksi agama sekaligus dan diskriminasi struktural oleh oknum-oknum otoritas politik, mulai dari yang terbawah (lurah, kades) hingga yang teratas.
2. Intoleransi Struktural
Intoleransi struktural adalah segala tindakan dan kebijakan oknum pemegang otoritas dalam institusi negara yang bertujuan atau mengakibatkan penafian hak orang lain dalam memilih keyakinan akibat kesalahpahaman atau disinformasi, juga kepentingan politik.
Kelompok minoritas yang disesatkan hingga dikafirkan dari seluruh arah cenderung dipandang tak punya nilai politis sama sekali, kalau bukan malah dianggap sangat merugikan bila dibela hak humaniter dan konstitusionalnya.
Keadaannya tambah runyam dan posisi kelompok minoritas ini lebih tragis lagi, bila rata-rata anggota dalam institusi pemerintah dan para politisi, baik dalam partai yang mengusung label “Islam” maupun yang mengklaim nasionalis, terpapar virus intoleransi dan sektarianisme. Akibatnya, fakta-fakta ironis berikut akan sangat mudah dijumpai:
a. Organisasi kebencian yang memasang kata “anti” dan menyebut nama kelompok muslim “Syiah” (baru pertama kali dalam sejarah, bahkan di dunia) diberi izin berdiri dan tercatat secara resmi oleh institusi pemerintah.
b. Seorang pejabat dan pemimpin pemerintahan daerah merasa dirinya pantas dan bangga meresmikan gedung organisasi provokatif tersebut.
c. Pejabat bupati merasa bebas menerbitkan surat edaran yang memuat instruksi kepada pemegang otoritas di bawah kekuasaannya untuk tidak mengizinkan pendirian gedung terhadap organisasi resmi kelompok minoritas yang sesat (bukan karena memang sesat, tapi karena terus disesat-sesatkan secara massif) ini.
Semua pandangan dan keyakinan Syiah, bahkan kadang isu sensitif yang para ulama Syiah enggan juga dilarang membahasnya, mudah diterima atau paling tidak, tidak dipersoalkan oleh sebagian masyarakat umum (non Syiah) bahkan kalangan intoleran pembenci Syiah
1) bila penyampai tidak dikenal sebagai tokoh Syiah atau penganut Syiah. Lebih diterima lagi bila penyampai dikenal sebagai ulama, kyai, ustadz, dan gus di tengah masyarakat umum.
2) bila penyampai tidak mengutip kata Syiah, tokoh imam dan ulama Syiah juga teks yang bisa dikaitkan dengan Syiah
3) bila penyampai menyelipkan candaan atau kelakar meski tak lucu;
4) bila yang disampaikan adalah isu historikal dan fikih yang mudah dipahami.
Namun bila yang disampaikan adalah info yang termuat dalam semua literatur Sunni dan Syiah atau pandangan logis, ditolak
1) bila penyampainya mengaku bermazhab Syiah atau dikenal sebagai tokoh Syiah;
2) bila penyampainya dikenal sebagai tokoh moderat yang toleran terhadap Syiah.
Anehnya, bila yang disampaikan adalah info palsu tentang ajaran Syiah, diterima dan dishare meski penyampainya dikenal pembenci Syiah.
Masih adakah harapan walau secercah untuk mengakhiri intoleransi sosial maupun struktural di tengah keruhnya telaga kehidupan sosial kita? Paling tidak, membuat kekeruhan itu tembus pandang agar makin banyak yang optimistis bahwa Indonesia punya masa depan yang toleran.