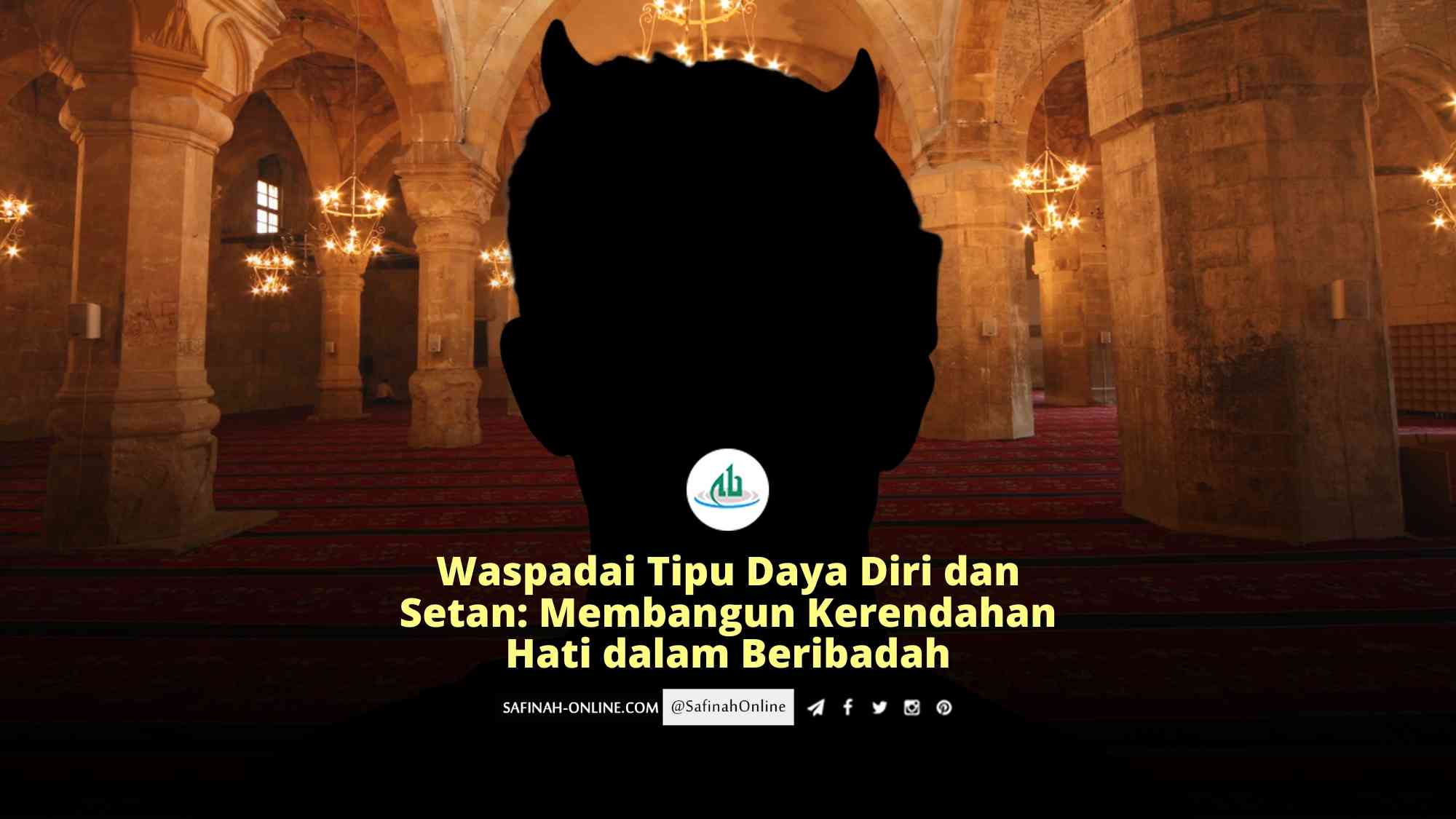Oleh Umar Shahab*
Pengantar
Setiap kali memasuki Ramadan dan khususnya Idulfitri atau Lebaran, komunitas Syiah di Indonesia selalu dihadapkan pada dua pilihan, mengikuti keputusan Pemerintah atau menetapkan sendiri kapan jatuhnya awal Ramadan dan Idulfitri.
Sekelompok orang, termasuk beberapa ustaz Syiah memutuskan mengikuti ketetapan Pemerintah dengan alasan ketetapan Pemerintah lebih meyakinkan karena selain berdasarkan rukyat, para perukyat Pemerintah didukung peralatan yang canggih.
Selain itu, Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei (selanjutnya disebut Rahbar), Marja’, panutan utama Syiah dunia, termasuk Indonesia, membenarkan (membolehkan) mengikuti ketetapan Pemerintah perihal awal Ramadan dan Idulfitri.
Bahkan, beberapa ikhwan mengklaim bahwa Rahbar mengharuskan penganut Syiah di mana pun mereka berada untuk mengikuti ketetapan Pemerintah masing-masing.
Alasan lain, penganut Syiah di Indonesia belum banyak jumlahnya, minoritas, yang dengan sendirinya riskan untuk berseberangan dan berhadap-hadapan dengan Pemerintah dan masyarakat.
Sementara itu, sebagian kelompok Syiah lainnya, khususnya yang tergabung dalam organisasi AHLULBAIT INDONESIA (ABI) memutuskan untuk menetapkan sendiri awal Ramadan dan Idulfitri karena menganggap metode penetapan awal bulan Hijriyah yang dianut Syiah berbeda dengan metode yang digunakan Sunni, yang dengan sendirinya menuntut komunitas Syiah untuk menetapkan sendiri awal bulan Hijriyah berdasarkan metode dan prinsip-prinsip fikih Syiah.
Baca: Doa Rasulullah SAW Melihat Hilal
Selain itu, karena banyak sekali ritualitas agama dan hukum fikih yang terkait erat dengan tanggal dan waktu, yang jika tidak dilaksanakan tepat waktu, atau paling tidak, diyakini diamalkan pada waktunya, akan bermasalah pada keabsahan dan atau afdhaliyyah–nya. Ambil contoh ritualitas malam-malam qadar (lailatul qadar) pada bulan Ramadan dan pelaksanaan zakat fitrah. Kedua ibadah ini sangat terikat dengan ketepatan waktu.
Zakat fitrah misalnya, hanya bisa dilaksanakan pada malam Idulfitri hingga sebelum pelaksanaan salat Ied. Demikian pula ritual lailatul qadar; ada amalan-amalan tertentu seperti salat-salat sunah khusus yang pelaksanaannya dikaitkan dengan malam 19, 21 dan 23 Ramadan.
Dengan demikian, jika penganut Syiah ingin amal ibadahnya yang terkait dengan tanggal dan waktu dilaksanakan sesuai fikihnya, maka tidak ada jalan lain kecuali menetapkan sendiri awal bulan Hijriyah.
Tentu ABI tidak asal ketok palu. Ada seperangkat persyaratan dan ketentuan fikih yang harus dipenuhi. Untuk itu ABI telah membentuk Lembaga Falak ABI dan Dewan Itsbat ABI yang bekerja setiap bulan untuk melakukan pengamatan hilal dari berbagai titik di berbagai daerah Indonesia, mulai dari Aceh (Barat) sampai Papua (Timur), dan kemudian menetapkan awal bulan Hijriyah berdasarkan prinsip-prinsip fikih sesuai fatwa dan pandangan Rahbar. Insya Allah ketetapan ABI ini dapat dipertanggungjawabkan secara syar’i.
Baca: Suaras DS: Tingkatkan Upaya Penyucian Diri dan Kepedulian Sosial di Bulan Suci Ramadhan
Langkah yang dipilih ormas ABI ini tentu bukan barang baru di Indonesia. Sejak masa penjajahan bahkan hingga kini masih banyak ormas Islam, pesantren-pesantren, perkumpulan-perkumpulan agama dan tokoh-tokoh agama yang menetapkan sendiri awal Ramadan dan Idulfitri. Mereka beralasan bahwa mereka merasa lebih mantap dengan ketetapan sendiri dan lagi pula punya hak yang sama dengan yang lain untuk menetapkan sendiri awal Ramadan dan Idulfitri.
Baru pada tahun 1980-an, Pemerintah, dalam hal ini Departemen atau Kementerian Agama, melibatkan ormas-ormas Islam untuk menetapkan bersama awal Ramadan dan Idulfitri melalui apa yang disebut dengan Sidang Itsbat. Cukup berhasil, namun tetap saja menyisakan perbedaan khususnya antara Muhammadiyah dan NU karena kedua ormas besar Islam ini memiliki perbedaan metode penetapan awal bulan Hijriyah yang cukup mendasar. Muhammadiyah menganut metode wujud al-hilal sedangkan NU menganut metode rukyat al-hilal.
Sekadar catatan, antara tahun 2010-2019 telah terjadi tiga kali perbedaan penetapan awal Ramadan dan Idulfitri antara NU/Pemerintah dan Muhammadiyah, yaitu tahun 1433, 1434 dan 1435 H, pada saat Pemerintah memutuskan awal Ramadan jatuh pada tanggal 21 Juli 2012, 10 Juli 2013 dan 29 Juni 2014, sedangkan Muhammadiyah menetapkan satu hari sebelumnya, yaitu 20 Juli 2012, 9 Juli 2013 dan 28 Juni 2014.
Baca: Agama dan Pemerintahan (1)
Demikian pula Idulfitri tahun 1432 dan 1436 H. NU/Pemerintah menetapkan jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011 dan 18 Juli 2015, sedangkan Muhammadiyah menetapkan jatuh pada tanggal 30 Agustus 2011 dan 17 Juli 2015.
Meski demikian, karena menganggap hal ini masuk kategori khilafiyah, Pemerintah Indonesia dan ormas-ormas Islam tidak mempersoalkannya. Apalagi mereka meyakini bahwa perbedaan adalah rahmat bagi umat Islam, sebagaimana hadis populer: “Perbedaan pendapat yang terjadi di antara umatku adalah rahmat”.
Baca: Agama dan Pemerintahan (2)
Adanya toleransi yang tinggi ini dari pihak Pemerintah dan masyarakat, bahkan terhadap beberapa jemaah tarikat yang menetapkan awal Ramadan dan Idulfitri bukan berdasarkan pada posisi hilal tetapi lebih pada pasang surut air laut, semakin memperkuat tekad ABI untuk menetapkan sendiri awal bulan Hijriyah berdasarkan metode dan prinsip-prinsip fikih Syiah. Karena selain tidak menyalahi peraturan dan undang-undang, ABI yakin Pemerintah dan Muslimin Ahlusunnah pun akan maklum.
Atas dasar itu, komunitas Syiah, atau lebih tepatnya sebagian penganut Syiah tidak perlu merasa khawatir bahwa penetapan awal Ramadan dan atau Idulfitri yang (mungkin) berbeda dengan Pemerintah akan menimbulkan pandangan negatif terhadap komunitas Syiah. Karena, selain sudah umum diketahui bahwa Syiah memang memiliiki perbedaan-perbedaan pandangan dengan Sunni, termasuk dalam hal penetapan awal bulan Hijriyah sehingga tidak perlu ditutup-tutupi. Maka masyarakat, termasuk komuntas Syiah, juga perlu diedukasi bahwa perbedaan adalah hal yang niscaya, lumrah dan tidak perlu ditakuti.
PANDANGAN FIKIH
Pada dasarnya fikih Syiah tidak mempersoalkan rukyat atau hisab untuk menetapkan awal bulan Hijriyah. Namun yang penting, apapun metodenya, ia menghasilkan kepastian atau setidaknya kemantapan hati, itminan, bahwa hilal telah terbit atau dalam istilah fuqaha’ Syiah disebut tsubut al-hilal.
Ayatullah Ali Sistani, salah satu Marja’ utama Syiah yang mukim di Najaf, Irak, menjelaskan bahwa terbitnya hilal (tsubut hilal) dapat diketahui melalui:
(1) kepastian (al’ilm) yang diperoleh melalui rukyat, tawatur, kemutawatiran dan sebagainya;
(2) itminan, kemantapan hati, yang diperoleh melalui syiya’, tersebarnya berita, atau lainnya yang bersumber dari sumber-sumber rasional;
(3) berlalunya 30 hari bulan Syakban, yang dengan itu (diyakini) terbitnya hilal Ramadan atau berlalunya tiga puluh hari bulan Ramadan, yang dengannya (diyakini) terbitnya hilal Syawal; dan
(4) kesaksian dua saksi adil.[1]
Hal yang sama juga dinyatakan Rahbar, hanya saja Rahbar menambahkan kriteria kelima, yaitu keputusan hakim syar’iy atau otoritas keagamaan. Bagi Rahbar, keputusan hakim syar’iy mengikat semua mukallaf yang ada di wilayah keputusannya[2]
Tidak demikian menurut pendapat Ayatullah Ali Sistani, keputusan hakim syar’iy tidak masuk kriteria metode penetapan hilal[3]
Kemudian, terkait adanya perbedaan di kalangan fuqaha Syiah mengenai metode rukyat, apakah rukyat harus dengan mata telanjang atau boleh menggunakan alat bantu seperti teleskop; Ayatulah Ali Sistani mensyaratkan rukyat dengan mata telanjang, tidak cukup dengan alat bantu[4], sedangkan Rahbar menganggap sama antara rukyat dengan menggunakan alat dan rukyat dengan mata telanjang[5]
Untuk lebih jelasnya, berikut penulis kutipkan beberapa fatwa Rahbar terkait fikih hilal yang penulis simpulkan dari kitab Ajwibah al-Istiftaat, kitab Daras Fikih, dan Jawaban-jawaban beliau sebagaimana tercantum dalam web resmi beliau, Leader.Ir.
- Awal bulan Hijriyah ditetapkan berdasarkan terbitnya hilal di awal bulan yang dapat diketahui melalui rukyat langsung oleh mukallaf sendiri, kesaksian dua orang ‘adil yang mengaku melihat bulan langsung, tersebarnya berita secara massif yang menimbulkan kepastian (al-ilm) bahwa hilal telah terbit, berlalunya 30 hari dan keputusan otoritas keagamaan atau hakim syar’iy.[6]
- Tolok ukur dalam menetapkan awal bulan Hijriyah adalah hilal yang terbenam sesudah terbenamnya matahari yang memungkinkan untuk dilihat sebelum ia tenggelam.[7]
- Rukyat hilal bisa dilakukan dengan menggunakan mata telanjang, al-ain al-mujarradah, atau dengan alat bantu, al-ain al-musallahah[8].
- Besar kecil, tinggi rendah dan luas atau lemahnya hilal tidak dapat dijadikan hujjah syar’iyyah, dasar agama, untuk menetapkan bahwa ini malam pertama atau malam kedua, kecuali jika dengan hal itu mukallaf memperoleh pengetahuan tertentu. Jika demikian, maka ia harus bertindak sesuai dengan pengetahuannya itu[9].
- Tidak disyaratkan bagi terjadinya tsubut al-hilal menyaksikannya dengan mata telanjang. Rukyat dengan alat bantu pun sudah cukup. Demikian juga jika diperoleh itminan (bahwa bulan telah terbit) melalui sains[10]
- Sekadar itminan, mantap hati pada perhitungan astronomis tidak ada artinya sama sekali, tetapi jika dia tahu atau mantap hatinya (melalui perhitungan astronomis itu) bahwa hilal telah lahir dan keberadaannya dimungkinkan untuk disaksikan, maka ia harus menindaklanjuti pengetahuan atau itminan–nya itu (yaitu puasa atau berlebaran, misalnya).[11]
- Jika dia tahu bahwa hilal telah lahir dan dimungkinkan untuk disaksikan, maka sesungguhnya ia telah tahu bahwa bulan sudah masuk. Oleh karena itu ia harus menindaklanjutinya dengan melaksanakan amalan awal bulan, sekalipun ia tidak menyaksikan hilal. [12]
- Jika seseorang berada di tanggal 29 Hijriyah tapi dia ragu apakah besok itu tanggal 30 atau tanggal 1 bulan berikutnya, sementara belum terbukti baginya bahwa hilal telah terbit, maka ia harus ihtiyath dengan menyempurnakan puasa 30 hari.
- Jika suatu negara tertentu, Islam atau non Islam, memutuskan awal bulan Hijriyah, tidak ada kewajiban bagi mukallaf untuk mengikutinya kecuali jika keputusan itu menimbulkan itminan bagi mukallaf bahwa hilal sudah terbit.
- Jika qhadi di negara Saudi Arabia memutuskan awal bulan Zulhijjah maka pelaksanaan ibadah haji mengikuti keputusan tersebut.[13]
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa:
- Rukyat hilal adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam menetapkan awal bulan Hijriyah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul saw: “Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal”.Oleh karena itu fatwa-fatwa terkait penetapan awal bulan Hijriyah, khususnya awal Ramadan dan awal Syawal berkutat di sekitar rukyat, terlepas apakah rukyat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan bantuan alat seperti teleskop dan sebagainya. Itu sebabnya, meskipun Rahbar sangat apresiatif dengan kemajuan teknologi astronomi dan menerima baik analisis ilmiah yang akurat, akan tetapi beliau tetap mensyaratkan rukyat untuk menetapkan awal bulan Hijriyah, seperti terlihat pada fatwa beliau tentang tidak cukupnya prediksi ilmiah atau hasil olah komputer yang memperihatkan keberadaan hilal untuk dijadikan dasar penetapan awal bulan Hijriyah[14].
Namun demikian, berbeda dengan kebanyakan fuqaha, Ayatullah Ali Khamenei tidak membatasi makna rukyat dalam pengertian melihat langsung hilal, tetapi bagi beliau, kondisi yang memungkinkan untuk melihat bulan, yang lazim disebut dengan istilah imkan al- rukyah atau qaabilan li al-ru’yah, ketika diketahui bahwa jika tidak karena suatu halangan yang merintangi penglihatan, seperi hujan dan sebagainya, posisi imkan al-rukyat tersebut sudah cukup untuk menetapkan tsubut al-hilal. Tsubut al-hilal kategori ini disebut dengan al-ru’yah al-muhaqqaqah.
- Mengetahui (al-ilm) akan terbitnya hilal atau meyakini dan merasa mantap, itminan, bahwa hilal telah terbit atau tidak terbit merupakan dasar utama untuk menetapkan awal bulan atau tidaknya bagi mukallaf. Dengan dasar ini mukallaf dapat mengatasi banyak hal yang menimbulkan keraguan tentang telah terbit atau tidak terbitnya hilal. Seperti misalnya jika Pemerintah Indonesia melalui Departemen atau Kementerian Agama menetapkan awal bulan Syawal dan mengaku ada saksi-saksi akan hal itu. Jika keputusan Pemerintah ini melahirkan kemantapan hati bagi mukallaf bahwa hilal telah terbit maka ia dapat atau bahkan harus menetapkan hal yang sama bagi dirinya.
KEPUTUSAN PEMERINTAH
Seperti disinggung di awal, sekelompok penganut Syiah di Indonesia lebih memilih mengikuti ketetapan Pemerintah daripada repot-repot menetapkan sendiri. Toh dibenarkan juga oleh Rahbar. Bahkan sebagian dari kelompok ini menganggap bahwa Pemerintah adalah hakim syar’iy atau otoritas keagamaan yang dimaksud dalam fatwa-fatwa Rahbar terkait penetapan awal Ramadan dan Idulfitri, sehingga dengan demikian wajib bagi penganut Syiah untuk mengikuti ketetapan Pemerintah perihal awal Ramadan dan Idulfitri. Benarkah demikian? Mari kita lihat fatwa-fatwa Rahbar mengenai hal tersebut di atas.
Pertama, terkait maksud dari kata dan istilah hakim atau hakim syar’iy dalam fatwa- fatwa Ayatullah Ali Khamenei di atas sama sekali tidak mengarah kepada pengertian Pemerintah, melainkan kepada pengertian yang umum dikenal oleh masyarakat Syiah, yaitu, al-faqih al-jami’ li al-syaraith, fakih yang memenuhi kualifikasi. Itu sebabnya Rahbar dalam fatwa-fatwanya, kadang menggunakan kata hakim, hakim syar’iy , wali faqih atau wali amr al-muslimin untuk maksud yang sama, sebagaimana dapat dilihat pada masalah 855, 856 dan 860 dalam kitabnya Ajwibah al-Istiftaat.[15]
Baca: Berbeda dalam Penetapan Awal Bulan tidak Berarti Menentang Pemerintah
Dalam masalah nomor 855 beliau menyatakan: “Jika (pengumuman televisi dan radio) menimbulkan itminan akan terbitnya hilal atau telah keluarnya keputusan Wali Faqih terkait hal itu (hilal Syawal) maka hal itu sudah cukup dan tidak perlu melakukan penelitian.[16]
Dalam masalah 856 beliau menyatakan: “Jika awal bulan tidak dapat ditetapkan melalui rukyat hilal, sekalipun di ufuk kota-kota tetangga yang posisi ufuknya sama, atau melalui kesaksian dua orang ‘adil atau melalui keputusan hakim maka wajib melakukan ihtiyath untuk memastikan awal bulan.[17]
Sedangkan dalam masalah 860 Ayatullah Ali Khamenei menyatakan bahwa: “… Dan demikian pula jika hakim syar’iy menetapkan adanya hilal maka ketetapannya merupakan hujjah syar’iyyah bagi semua mukallaf. Mereka harus mengikutinya”.[18]
Bahkan di tempat lain beliau menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah al-mujtahid al-jami’ li al–syaraith.
Ketika beliau ditanya: “Apa yang dimaksud bahwa seorang mujtahid harus menetapkan keputusan perihal rukyat hilal supaya mengikat semua orang? Dan kepada siapa saja ketetapannya itu berlaku”? Beliau menegaskan: “Yang dimaksud dengan al-hakim adalah al-mujtahid al-jami’ li al-syaraith, dan tentunya wali faqih adalah pihak yang paling utama”.[19]
Penegasan makna hakim syar‘iy sebagai mujtahid oleh Rahbar ini diamini oleh hampir semua faqih Imamiyah baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakkhirin.
Baca: Serangkaian Pesan dan Tuntunan Praktis Al-Quran dalam Wejangan Imam Ali Khamenei
Dalam WikiSyi’ah.Net, tema al–hakim al-syar’iy dinyatakan bahwa: “Al-hakim al-syar’iy atau hakim al-syar’i ialah seseorang yang memiliki wilayah atau otoritas atas kaum Muslimin. Istilah ini dalam fikih biasanya ditujukan kepada seorang faqih yang memenuhi kualaifikasi, jami’ li al-syaraith, karena ia memiliki otoritas keagamaan, al-hakimiyyah al-syar’iyyah, sebagai pengganti para Maksum.
Namun demikian, terdapat perbedaan di kalangan fuqaha’ terkait batasan otoritasnya. Sebagian berpendapat bahwa otoritasnya hanya berlaku pada sebagian hal saja, seperti urusan anak yatim dan harta yang tidak diketahui pemiliknya, tetapi sebagian lain berpendapat bahwa otoritasnya sama dengan otoritas para Maksum.[20]
Dengan demikian, menerjemahkan istilah hakim syar’iy sebagai Pemerintah adalah keliru berat dan bertentangan dengan urf Syiah.
Kedua, sama sekali tidak ada fatwa Ayatullah Ali Khamenei perihal wajibnya pengikut Syiah mengikuti ketetapan Pemerintah tempat dimana mukallaf tinggal, terkait awal Ramadan dan atau Idulfitri.
Sepertinya pihak yang menyimpulkan hal ini salah kutip atau salah tafsir atas fatwa Ayatullah Ali Khamenei terkait hal ini.
Ada dua fatwa Ayatullah Ali khamenei yang biasanya dijadikan sandaran. Pertama, fatwa nomor 856 dan kedua fatwa nomor 868 dari kitab Ajwibah al-Istiftaat. Mari kita lihat kedua fatwa ini.
Fatwa nomor 856:
Pertanyaan: “Jika awal Ramadan atau Idulfitri tidak dapat ditetapkan karena hilal tidak dapat dilihat disebabkan oleh mendung atau faktor-faktor lainnya, sementara bilangan bulan Syakban atau Ramadan belum genap 30 hari, apakah boleh bagi kami yang tinggal di Jepang menetapkan puasa atau Idulfitri berdasarkan ufuq Iran? Atau bolehkah kami mengikuti kalender? Apa yang harus kami lakukan?
Jawaban: “Jika awal bulan tidak dapat ditetapkan berdasarkan rukyat hilal, sekalipun dengan mengikuti ufuk kota-kota tetangga yang seufuk, juga tidak bisa ditetapkan melalui kesaksian dua orang ‘adil atau keputusan al-hakim, maka wajib hukumnya melakukan ihtiyath agar ada kepastian awal bulan. Adapun rukyat hilal di Iran, yang terletak di barat Jepang, tidak ada artinya sama sekali bagi orang yang tinggal di Jepang[21].
Fatwa di atas diklaim beberapa pihak sebagai mewajibkan penganut Syiah mengikuti ketetapan Pemerintah tempat ia tinggal karena fatwa tersebut di atas melarang penganut Syiah yang tinggal di luar Iran untuk mengikuti ketetapan Pemerintah Republik Islam Iran perihal awal Ramadan dan Idulfitri.
Sebuah kesimpulan yang jauh panggang dari api karena selain tidak ada pernyataan kewajiban mengikuti ketetapan Pemerintah tempat tinggal mukallaf, juga tidak ada relevansi antara tidak boleh menetapkan awal Ramadan dan Idulfitri mengikuti ketetapan Pemerintah Republik Islam Iran bagi seseorang yang tinggal di Jepang yang ufuknya berbeda dengan ufuk Iran dengan keharusan mengikuti ketetapan Pemerintah tempat tinggalnya. Dua subjek yang berbeda. Apalagi dalam fatwa di atas disebutkan bahwa alasan tidak boleh mengekor ke Iran bukan karena si penanya tinggal di luar Iran tapi karena ufuk tempat tinggal si penanya, Jepang, beda dengan ufuk Iran. Dan memang syarat untuk mengikuti ketetapan hilal wilayah lain bagi wilayah yang tidak melihat hilal dalam pandangan Rahbar adanya kesamaan ufuk, ittihad al-ufuq, antara kedua wilayah.[22]
Kalau toh dalam fatwa nomor 856 di atas memberikan arahan untuk mengikuti keputusan al-hakim selain kesaksian dua orang ‘adil dan melakukan ihtiyath jika tidak melihat bulan, al-hakim yang dimaksud dalam fatwa tersebut bukan Pemerintah tapi mujtahid yang jami’ li al-syaraith sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Fatwa nomor 868:
Pertanyaan: “Dalam hal boleh mengikuti pengumuman suatu negara terkait rukyat hilal, di mana pengumuman itu merupakan standar ilmiah perihal terbitnya hilal bagi negara-negara lain, apakah disyaratkan negara tersebut harus Negara Islam atau boleh mengikutinya sekalipun negara tersebut zalim dan fajir?
Jawaban: “Tolok ukur dalam hal tersebut di atas ialah diperolehnya itminan pada mukallaf bahwa hilal telah terbit di wilayah tersebut.[23]
Fatwa di atas diklaim oleh sebagian kawan-kawan menunjuk pada keharusan atau setidaknya lebih baik mengikuti ketetapan Pemerintah daripada repot-repot melakukan istihlal sendiri, apalagi alat yang digunakan Pemerintah canggih dan rukyat dilakukan di banyak titik.
Benar, alat-alat yang digunakan perukyat Pemerintah canggih dan dilakukan di banyak titik, akan tetapi fakta di lapangan tidak jarang Pemerintah menyandarkan ketetapannya pada kesaksian-kesaksian perukyat telanjang mata yang telah disumpah ketika para perukyat pengguna alat canggih tidak menyaksikan hilal seperti terindikasi pada kasus penetapan awal Ramadan tahun 1441 H/2020, tahun ini, ketika menurut T. Djamalauddin, ahli astronomi terkemuka Indonesia yang sering dilibatkan dalam sidang-sidang itsbat Departemen atau Kementerian Agama bahwa hasil rukyat hilal awal Ramadan di Indonesia yang menetapkan awal Ramadan jatuh pada tanggal 24 April 2020, boleh (patut) diragukan secara astronomi karena posisi hilal masih di bawah batas minimal astronomis untuk wilayah Indonesia sehingga tidak mungkin dirukyat di Indonesia.[24]
Selain itu, pada fatwa nomer 868 di atas sama sekali tidak terdapat pernyataan yang mengharuskan penganut Syiah agar mengikuti ketetapan Pemerintah. Fatwa di atas hanya membolehkan atau lebih tepatnya membenarkan penganut Syiah untuk mengikuti ketetapan Pemerintah tempat ia tinggal, tetapi dengan satu catatan, yaitu bahwa ketetapan tersebut melahirkan itminan, kemantapan hati, pada mukallaf bahwa hilal telah terbit. Jika mukallaf ragu, maka ia tidak boleh mengikuti ketetapan tersebut dan ia harus beralih ke salah satu metode penetapan lain yang memberinya kepastian atau itminan.
Dari fatwa nomor 868 di atas, terlihat jelas bahwa posisi ketetapan Pemerintah hanya sebagai sarana bagi lahirnya itminan pada seorang mukallaf bahwa hilal telah terbit, sebagaimana rasa itminan itu bisa juga muncul dari hal lain seperti prediksi astronom[25] dan sebagainya, bukan sebagai tolok ukur penetapan awal bulan Ramadan atau Idulfitri karena tidak hujjah secara syar’iy.
Selanjutnya perlu ditambahkan di sini bahwa penetapan hilal dalam fikih Syiah, apalagi dengan mengacu pada fatwa Ayatullah Sistani yang mengangap ketetapan hakim syar’iy tidak berlaku pada penetapan awal Ramadan dan Idulfitri, tidak masuk ranah “publik”, tapi ranah pribadi, dalam arti bahwa adalah kewajiban setiap mukallaf memastikan bagi dirinya atau paling tidak memiliki itminan bahwa hilal sudah terbit, melalui empat atau lima kriteria metode penetapan hilal yang umum diketahui.
Ketiga, perlu ditegaskan di sini, sebagaimana terlihat pada fatwa Rahbar yang menyatakan bahwa penetapan awal Zulhijjah untuk ibadah haji mengikuti ketetapan qhadi negara Arab Saudi bahwa penetapan awal Zulhijjah untuk jemaah haji berbeda dengan penetapan awal Ramadan dan Idulfitri. Untuk haji mengikuti keputusan Pemerintah Saudi sedangkan untuk awal Ramadan, Idulfitri dan Iduladha bagi selain jemaah haji mengikuti aturan hukum yang telah dijelaskan di atas.
KHATIMAH
Menutup tulisan ini, penulis ingin mengingatkan semua penganut Syiah di Indonesia tentang beberapa hal pokok berikut dalam fikih Syiah Imamiyah yang harus menjadi perhatian sungguh-sungguh semua penganut Syiah karena terkait keabsahan dan kesempurnaan ibadah mereka, yaitu:
- Sudah merupakan kesepakatan seluruh fuqaha Syiah Imamiyah bahwa dalam melaksanakan syariat, seorang Syi’i dibenarkan untuk memilih salah satu di antara tiga jalan atau cara berikut:
- Ijtihad, yaitu upaya memahami hukum Islam yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan saksama oleh orang-orang yang dianggap kompeten, berdasarkan dalil-dalil syar’iy berupa Al-Quran, Sunnah, Akal dan Ijma’.
- Ihtiyath, yaitu mengambil sikap kehati-hatian dengan memilih opsi yang pasti di antara persoalan-persoalan yang diperselisihkan oleh para fuqaha, misalnya kewajiban membaca tasbih dalam ruku’ dan sujud, apakah cukup satu kali atau harus tiga kali; seseorang yang memilih jalan ihtiyath harus melakukannya tiga kali karena dengan membaca tasbih tiga kali ia telah memastikan bahwa ia telah memenuhi kewajiban membaca tasbih.
- Taqlid, mengikuti fatwa atau pandangan seorang mujtahid yang memenuhi kualifikasi, yaitu kompetensi ijtihad, ‘adil (tingkat kesalihan tinggi yang membuat seseorang tidak melakukan dosa besar walaupun sekali dan tidak melakukan dosa kecil yang berulang), dan, menurut sebagian besar fuqaha, sang mujtahid tersebut harus a’lam, diyakni paling berilmu di antara mujtahid yang ada. Meskipun tidak ada batasan jumlah mujtahid dimaksud, tetapi dalam pelaksanaannya hanya muncul beberapa orang saja setiap zaman yang lazim disebut dewasa ini sebagai Marja’ atau marji’ taqlid. [26]
- Untuk memilih jalan ijtihad, seseorang dituntut untuk menguasai secara mendalam berbagai disiplin ilmu agama, terutama fiqih dan ushul al-fiqih, hadis dan rijal, dan tentu saja tafsir dan bahasa Arab. Untuk itu biasanya seorang talabeh, santri, harus menempuh jenjang pendidikan yang panjang sampai kemudian diakui sebagai mujtahid yang telah memenuhi kompetensi ijtihad. Dengan demikian, jika ia belum mencapai tingkat mujtahid, ia tidak diperkenakan berijtihad atau menyimpulkan sendiri hukum agama, tetapi ia harus ber-taqlid kepada mujtahid yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dijelaskan di atas atau melakukan ihtiyath. Jika tetap dilakukannya, bukan hanya berdosa, tetapi semua amal ibadah hasil “ijtihad”-nya dianggap tidak sah.[27]
- Secara umum, amal ibadah yang dilakuan oleh orang awam (bukan mujtahid) tanpa ber-taqlid kepada seorang mujtahid yang memenuhi kualifikasi atau tanpa ihtiyath maka amal ibadahnya dikategorikan tidak sah.[28] Demikian pula jika ia “ber-taqlid” kepada seseorang yang bukan mujtahid jami’ li al-syaraith.
* Ketua Dewan Syura AHLULBAIT INDONESIA (ABI)
[1] https://www.sistani.org/arabic, Al-Sayyid Ali al-Husaini al-Sistani, Minhaj al-Shalihin, Bab al-Shaum, Pasal Sembilan.
[2] Al-Sayyid Ali al-Husaini al-Khamenii, Ajwibah al-Istiftaat, Bagian Pertama (Beirut: Dar al-Wasilah, 1995) hal. 259.
[3] Al-Sistani, loc. cit
[4] Ibid.
[5] Muhammad Ridha Musyafiqi Pur, Daras Fikih Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamenei (Jakarta: Al-Huda, 2010)
hal. 248
[6] Al-Khamenei, op. cit. hal. 260.
[7] Ibid. hal 256
[8] Musyafiqi, op. cit. hal. 248
[9] Al-Khamenei, op. cit. hal. 259
[10] https//www. archive.org: maktabah al-Imam al-Khamenei, Bab al-Shaum, hal. 79.
[11] Ibid. hal. 80
[12] Ibid. hal. 79.
[13] https//www. Leader. Ir, Ahkam al-Shaum: Mengikuti Ahlussunnah Perihal Rukyat Hilal
[14] Musyafiqi, op. cit. hal. 248
[15] Lihat Al-Khamenei, op. cit . hal. 256, 257 dan 258.
[16] Ibid. hal. 256
[17] Ibid. hal, 257
[18] Ibid. hal 258
[19] https//www.leader.ir., Ahkam al-shaum: hukm al-hakim, no. 42
[20] WikiSyi’ah adalah ensiklopedi elektronik di bawah Lembaga Majma’ Ahlulbait Internasional yang berpusat di Teheran, Iran. Ditulis dalam sepuluh bahasa, yaitu: Persia, Arab, Inggeris, Prancis, Spanyol, Jerman, Rusia, Indonesia, Urdu, dan Turki.
[21] Al-Khamenei, op.cit., Permasalahan nomer 856, hal. 256.
[22] Al-Khamenei, ibid., permasalahan nomer 857, hal. 257
[23] Al-Khamenei, op. cit., permasalahan no. 868, hal 260
[24] https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/04/24/makna-fisis-hisab-posisi-hilal-dan-kriteria-imkan-rukyat
[25] Lihat https//www.leader.ir., Ahkam al-shaum, hushul al-itminan bi ru’yat al-hilal.
[26] Lihat https//leader. Ir., Tahril al-Wasilah: Mukaddimah
[27] Ibid. masalah 20
[28] loc.cit.