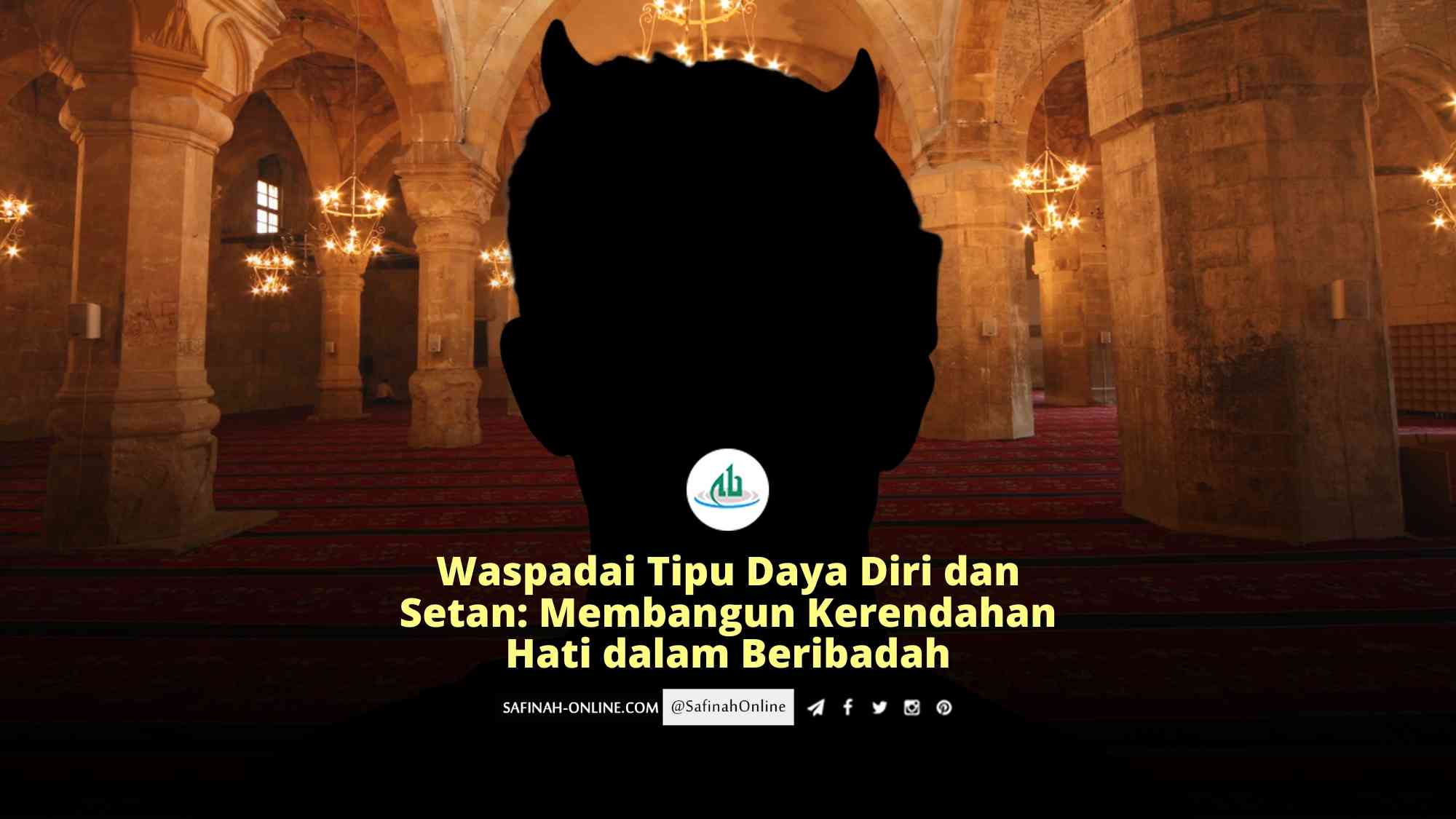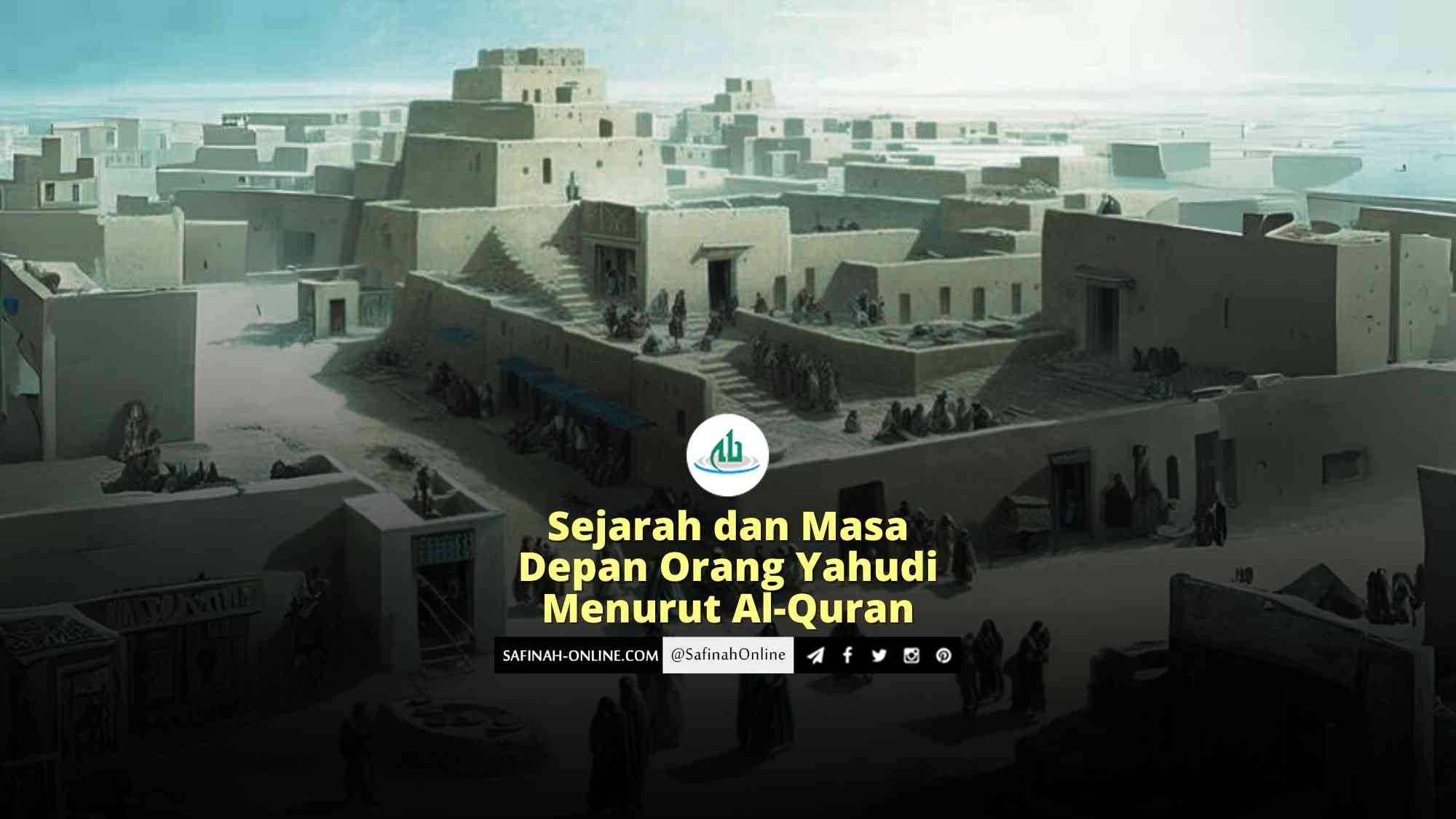Rasulullah SAW bersabada;
Rasulullah SAW bersabada;
إذا أحبَّ الله عبداً من أُمَّتي قذف في قلوب أصفيائه وأرواح ملائكته وسكان عرشه محبَّته; ليحبُّوه، فذلك المحبُّ حقّاً، طوبى له ثُمَّ طوبى له، وله عند الله شفاعةٌ يوم القيامة.
“Ketika Allah mencintai seorang hamba di antara umatku maka Dia menghunjamkan kecintaan kepadanya pada hati hamba-hamba pilihannya serta ruh para malaikat dan penghuni Arasy-Nya agar mereka mencintainya dengan cinta sejati. Maka beruntunglah dia, beruntunglah dia, dan dia mendapat syafaat di sisi Allah pada hari kiamat.”[1]
Ketaatan kepada Allah ada yang bertolak dari pengetahuan akan adanya Sang Pencipta (mabda’) dan hari akhirat (ma’ad), termasuk karena mengikuti keyakinan orang tua atau ulama, misalnya, sebagaimana terjadi pada kebanyakan orang. Ketaatan juga ada yang bertolak dari argumentasi, sebagaimana dialami sebagian kalangan terdidik.
Semua ketaatan ini berbeda dengan ketaatan yang bertolak dari pengetahuan yang disusul dengan cinta. Cinta yang dimaksud adalah cinta pada jenjang-jenjangnya yang tertinggi, bukan cinta sekedarnya yang tentu tak terpisahkan dari diri setiap Muslim.
Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut;
Pertama, pengetahuan sebagai sumber ketaatan tidak selalu membuah hasil yang diinginkan. Buktinya, sebagian orang fasik tetap saja tak segan-segan berbuat maksiat meskipun mengetahui dan meyakini adanya mabda’ dan ma’ad. Sedangkan jika sumbernya adalah cinta dengan pengertiannya seperti yang maksud tadi maka tidak akan lepas dan menyimpang dari kepatuhan.
Karena itu, kepeduliaan orang tua kepada anak yang sangat dicintainya untuk menyediakan segala sesuatu yang diminta oleh anak selagi permintaan itu tidak membuatnya celaka tak jarang lebih besar daripada kepedulian kepada ketaatan kepada Allah yang secara rasional wajib baginya. Ini terjadi tentu karena kecintaan kepada anak lebih besar daripada kecintaan kepada Allah.
Diriwayatkan bahwa Imam Jakfar Al-Shadis as berkata;
ما أحبَّ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ مَنْ عصاه.
“Allah Azza wa Jalla tidak mencintai orang yang bermaksiat kepadaNya.”
Beliau kemudian bertamsil dengan syair:
تعصي الإله وأنت تُظْهِرُ حبَّه *** هذا محالٌ في الفعال بديعُ
لو كان حبُّك صادقاً لأطعتهُ *** إنَّ المحبَّ لمن يحبُّ مطيعُ
“Kamu bermasiat kepada Tuhan sembari berlagak mencintaiNya. Ini jelas perbuatan yang mustahil. Jika cintamu tulus maka kamu pasti mematuhiNya, sebab pecinta pasti patuh kepada yang dicintainya.”[2]
Kedua, kepatuhan yang berasal dari cinta adalah kepatuhan manusia bermental merdeka, dan mereka inilah yang menyembah Allah SWT karena Dia memang layak disembah. Sedangkan kepatuhan yang berasal hanya dari pengetahuan semata adalah kepatuhan manusia bermental pedagang, atau budak. Yang bermental pedagang menyembahNya demi mendapatkan laba dan keuntungan berupa surga, sedangkan yang bermental budak menyembahNya karena takut mendapatkan siksa dan neraka.
Imam Ali bin Abi Thalib as berkata;
إنَّ قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإنَّ قوماً عبدوا الله رهبةً فتلك عبادة العبيد، وإنَّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار.
“Sesungguhnya ada suatu kaum yang menyembah Allah karena berharap pahala maka itulah ibadah para pedagang, dan ada pula suatu kaum yang menyembah Allah karena takut maka itulah ibadah para budak, dan ada lagi kaum yang menyembah Allah karena bersyukur maka inilah ibadah orang-orang merdeka.”[3]
Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Imam Jakfar Al-Shadiq as berkata;
قوم عبدوا الله ـ عزَّوجلَّ ـ خوفاً فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله ـ تبارك وتعالى ـ طلب الثواب فتلك عبادة الأُجراء، وقوم عبدوا الله ـ عزّوجلّ ـ حبَّاً له فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
“Ada suatu kaum menyembah Allah Azza wa Jalla karena takut maka itulah ibadah hamba sahaya. Ada pula suatu kaum yang menyembah Allah Tabaraka wa Ta’ala karena berharap pahala maka itulah ibadah para buruh. Ada lagi suatu kaum kaum yang menyebah Allah Azza wa Jalla karena cinta maka itulah ibadah orang-orang merdeka, dan itulah sebaik-baik ibadah.”[4]
(Bersambung)
[1] Bihar Al-Anwar, jilid 70, hal. 24.
[2] Bihar Al-Anwar, jilid 70, hal. 15.
[3] Nahjul Balaghah, hikmah 237.
[4] Al-Wasa’il, jilid 1, hal. 62, bab 9 Muqaddimat Al-Ibadat, hadis 1.