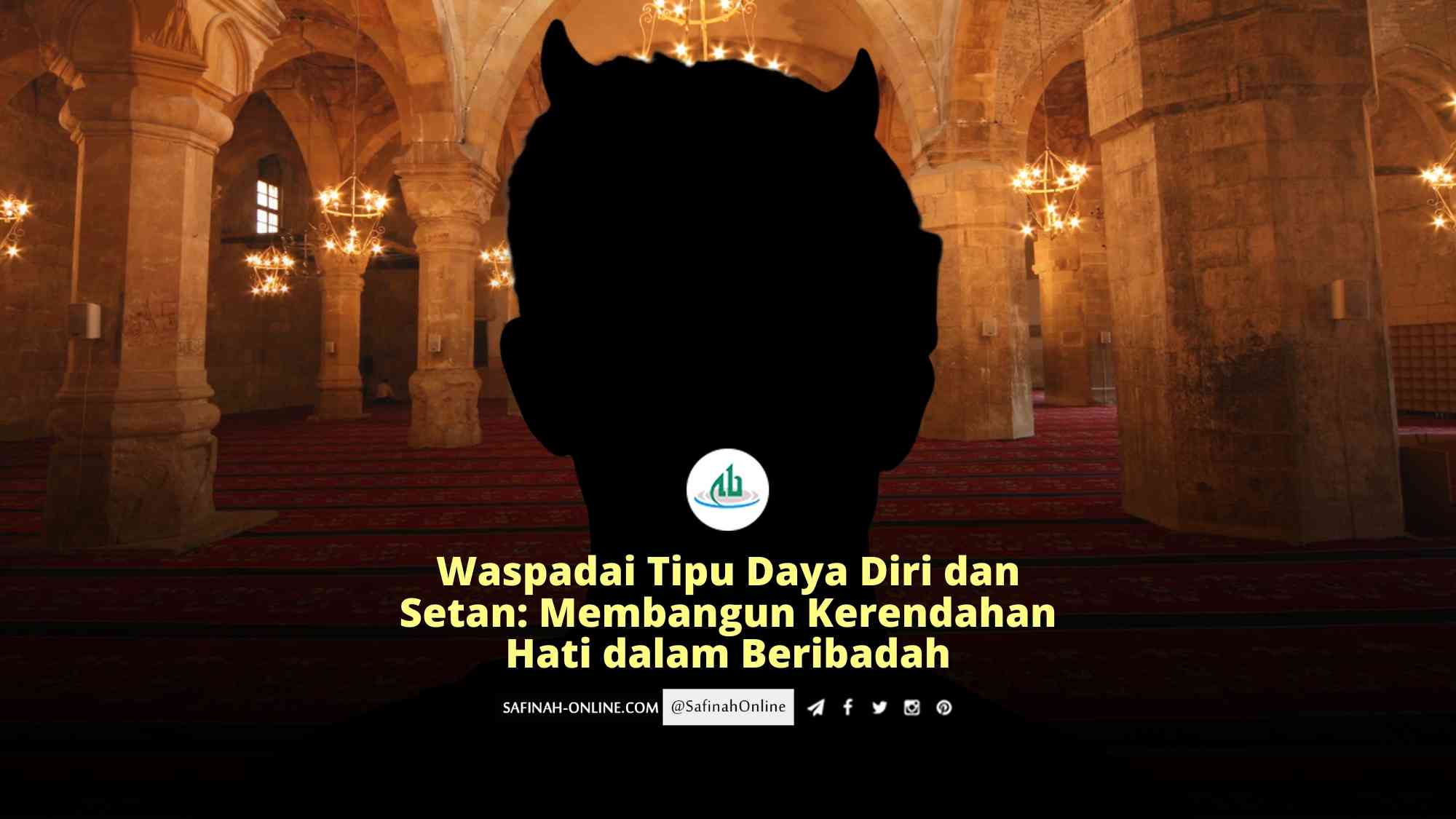Oleh Dr. Muhsin Labib,MA
Fatwa
Dalam kamus Lisanul Arab, Imam Ibnu Mandzur menyatakan bahwa kata “futya” atau ”futwaay” adalah dua isim (kata benda) yang digunakan dengan makna al-ifta’ (fatwa, dalam bahasa Indonesia). Kedua isim tersebut berasal dari kata “wa fataay”. Karena itu, dinyatakan, “Aftaitu fulaanan ru’yan ra`aaha idza ’abartuhaa lahu (aku memfatwakan kepada si fulan sebuah pendapat yang ia baru mengetahui pendapat itu jika aku telah menjelaskannya kepada dirinya).” “Wa aftaituhu fi mas`alatihi idza ajabtuhu ’anhaa (aku berfatwa mengenai masalahnya jika aku telah menjelaskan jawaban atas masalah itu).” [ juz 15, hal. 145]
Dalam Kitab Mafaahim Islaamiyyah, diterangkan sebagai berikut, ”Secara literal, kata ‘al-fatwa’ bermakna ‘jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-perundangan yang sulit’. Bentuk jamaknya adalah fataawin dan fataaway. Jika dinyatakan aftay fi al-mas`alah: menerangkan hukum dalam permasalahan tersebut. Sedangkan al-iftaa` adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undang-undang, dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya (ibaanat al-ahkaam fi al-mas`alah al-syar’iyyah, au qanuuniyyah, au ghairihaa mimmaa yata’allaqu bisu`aal al-saail). Al-muftiy adalah orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau menyampaikan fatwa di tengah-tengah masyarakat. Mufti adalah seorang faqih yang diangkat oleh negara untuk menjawab persoalan-persoalan agama. Sedangkan menurut pengertian syariat, tidak ada perselisihan pendapat mengenai makna syariat dari kata al-fatwa dan al-iftaa’ berdasarkan makna bahasanya.
Karena itu, fatwa secara syariat bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari masalah-masalah aktual, yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-Quran, Sunnah Nabawiyyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Jika mereka diharuskan memiliki kemampuan itu, yakni hingga mencapai taraf kemampuan berijtihad, niscaya pekerjaan akan terlantar, dan roda kehidupan akan terhenti…”[Mafaahim al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 240].
Tindakan memberi fatwa disebut futya atau ifta, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut mustafti. Peminta fatwa bisa perseorangan, lembaga, ataupun siapa saja yang membutuhkannya.
Futya pada dasarnya berupa profesi independen. Namun di banyak negara Muslim, ia menjadi terkait dengan otoritas kenegaraan dalam berbagai cara. Dalam sejarah Islam, sejak abad pertama hingga ketujuh Hijriyah, penguasalah yang mengangkat ulama bermutu sebagai mufti. Namun, pada masa-masa selanjutnya, pos-pos resmi futya diciptakan, sehingga mufti menjadi jabatan kenegaraan yang bersifat hierarkis, meski tetap dalam fungsi keagamaan.
Bayangkan bila pembuat fatwa yang berada dalam perkumpulan sejumlah orang yang dianggap para pemuka agama dan mengaku ulama serta diyakini banyak orang sebagai referensi pemerintah dan banyak pemegang otoritas negara adalah sosok ekstremis, intoleran, pembenci Pancasila, bahkan teroris.
Apa jadinya bila frasa mulia yang cenderung dipahami secara salah dan ngawur menjadi dasar aksi brutal massa yang mengakibatkan tercerabutnya hak untuk menghirup oksigen, menyulap anak jadi yatim, wanita jadi janda, dan ratusan bahkan ribuan warga tak bersalah menjadi korban kolosalisasi “fatwa”.
Adalah tragis bila fatwa menjadi hak kaum ekstremis. Tak bisa dibayangkan, bagaimana jadinya jika produk fatwa “ekstrimis” itu dianggap begitu saja oleh awam yang terbakar api provokasi sebagai lisence to kill, persekusi, dan segala bentuk vandalisme.
Fatwa Lembaga Non Negara dan Fatwa Negara
Patut digarisbawahi bahwa dalam institusi negara yang tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar dan asas, fatwa semestinya berupa produk konstitusi, bukan hasil kongkow sejumlah orang di luar lembaga yudikatif. Itulah fatwa formal dan konstitusional yang nyata-nyata mengikat setiap warga negara.
Dalam konstitusi dan UUD, fatwa adalah produk hukum yurisprudensi yang menjadi wewenang lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang no. 4 tahun 2004 atau yang lebih purba lagi, dalam Staatsblad 1847 no. 23, pasal 22 AB. Dengan demikian, produk hukum apapun yang tidak dikeluarkan lembaga yudikatif tidak memiliki legal standing, bahkan bisa dianggap ilegal hingga inkonstitusional.
Bila wewenang mengeluarkan fatwa diperoleh dari lembaga non negara, maka itu berarti lembaga tersebut memberikan wewenang kepada dirinya sendiri. Bila subjek pemberi wewenang adalah objek penerima wewenang itu sendiri, maka hal itu meniscayakan paradoks.
Bila wewenang itu diperoleh dari luar lembaga non negara, maka haruslah diberikan oleh lembaga yang lebih tinggi. Sedangkan lembaga non negara bukan bagian dari struktur negara, sehingga wewenang yang diklaimnya tidak valid.
Bila lembaga keagamaan yang membubuhkan kata majelis itu memperoleh wewenang dari negara dan menjadi bagian dari struktur negara, maka konskuensinya, agama Islam menjadi bagian dari konstitusi negara. Bila agama Islam menjadi bagian dari konstitusi, maka negara dengan sendirinya menafikan Pancasila sebagai dasarnya.