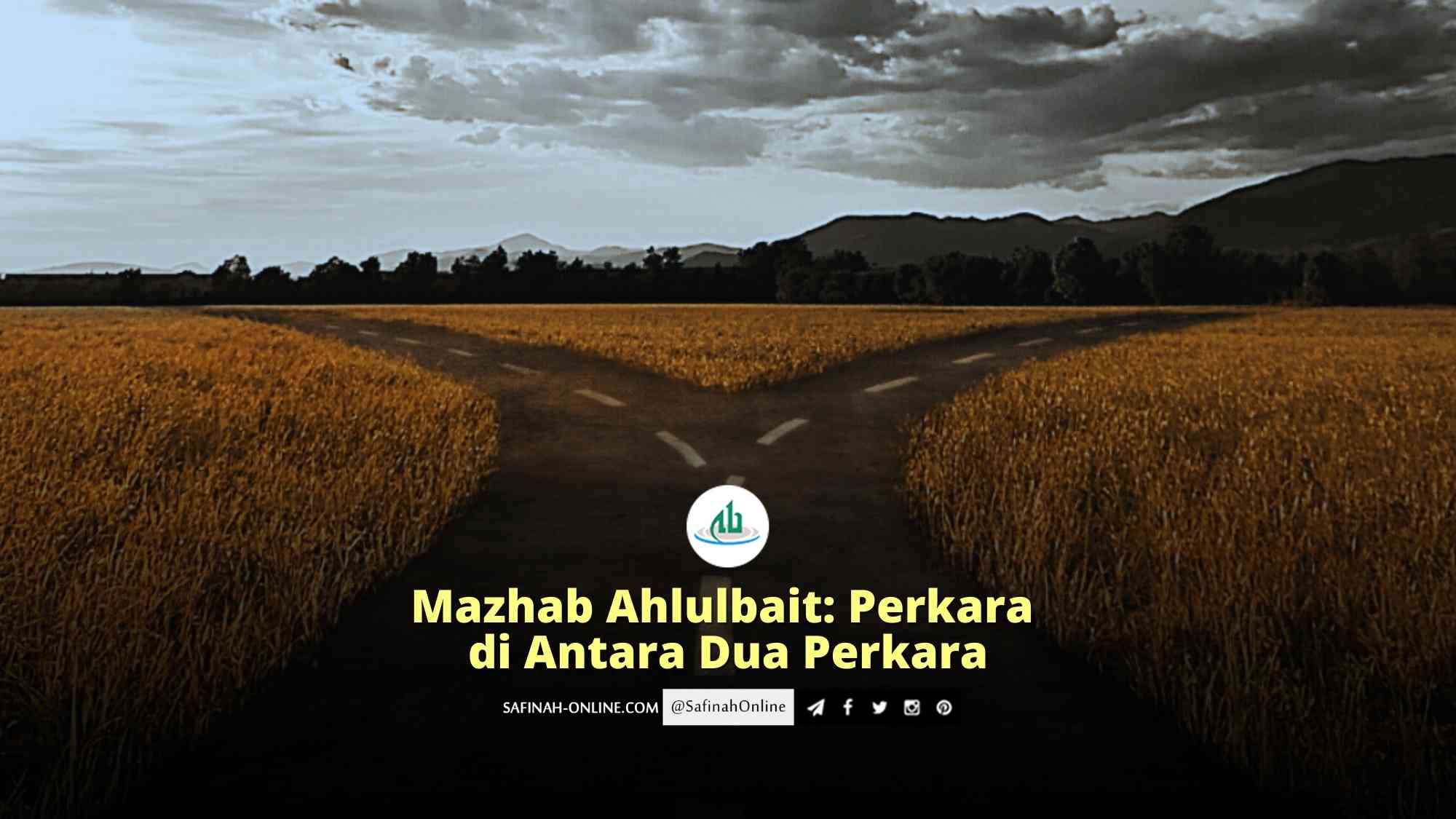Dr. Muhsin Labib
Agama dianut dan dihayati berkat hidayah Tuhan. Pilihan atau ikhtiar para penganut agama karenanya bukan memilih agama A, B, atau C. Tapi bagaimana merawat hingga menyempurnakan dan mempraktikkan ajaran agamanya agar sesuai keinginan Tuhan.
Kerap diabaikan banyak orang saat menyempurnakan dan mempraktikkan agama, mazhab, dan ideologinya adalah keharusan memahami konsekuensi praktis dan risiko sosial dalam aneka aspeknya. Sikap abai inilah yang membuat banyak orang “beragama” mengalami guncangan teologis cukup berat. Terlebih jika keyakinan agamanya terbilang minoritas yang menjadi objek diskriminasi.
Baca: Fikih Quest 63: Aqiqah dalam Mazhab Ahlulbait
Banyak faktor yang mengakibatkan guncangan itu.
Antara lain:
- Ikut-ikutan figur yang terlanjur diagungkan dan dianggap sebagai representasi kebenaran. Saat figurnya mengalami guncangan teologis akibat miss-epistemik, para pengikutnya pun ikut “berjoget” bersamanya.
- Ekspektasi yang keliru. Saat posisi sosial yang diincar lenyap, ia pun terguncang dan koprol sana-sini. Fenomena ini kerap terjadi di kancah politik.
- Relasi sosial atau kedekatan personal dalam interaksi bisnis atau ikatan kemitraan. Ketika relasi memburuk atau terputus, keyakinan atau ideologi yang dipilih berdasar kepercayaan dan kekaguman pada mitranya otomatis terputus.
- Beratnya tekanan dan kegagalan dalam beradaptasi dengan lingkungan keyakinan atau ideologi yang mengakibatkan kecanggungan dan miskomunikasi. Ketika adaptasi gagal, semangat dan antusiasme teologis dan ideologisnya ikut menguap.
- Terusir dari komunitas keyakinan atau ideologi sebelumnya lantaran divonis cacat moral akibat perilaku buruk atau fitnah yang menimpa. Faktor ini kemudian mendorongnya memasuki atmosfer baru dalam suatu komunitas dengan keyakinan baru. Saat perilaku buruknya terendus sehingga lagi-lagi ditolak oleh komunitas keyakinan baru tersebut, ia pun akan kembali ke komunitas lamanya sambil menjelek-jelekkan komunitas barunya.
- Mengira keyakinan baru yang dianutnya akan direspon oleh komunitasnya dengan jaminan sosial dan finansial sebagai ganti rugi atau semacam garansi atas keputusannya untuk bergabung.
- Menyangka keyakinan yang baru dianutnya tak menuntutnya berpikir serius (hanya cukup menyatakan diri sebagai penganut) dan bertanggung jawab atas kehidupan sosialnya sendiri. Saat ngeh tak sanggup menganutnya sesuai standar baku keyakinan baru, ia kontan mengalami turbulensi dan mulai menunjukkan perubahan pandangan dan sikap dalam celoteh-celoteh miring atau membuat koloni sendiri.
- Langsung “beragama” via emosi dan histori tanpa memulainya dari konsep kewenangan yang meniscayakan kepatuhan hierarkis dalam bersikap dan bertindak. Manakala tak sanggup menjinakkan egonya dalam menghadapi konsekuensi berat itu, ia akan cenderung membela diri dengan ujaran-ujaran apologetik yang bertendensi pada penolakan teologis.
Baca: ABI DAN SENSE OF CRISIS
Itulah sebabnya, mengapa akal sehat berikut logika perlu dijadikan mercusuar sekaligus juri dalam merawat, menyempurnakan, hingga mempraktikka keyakinan teologis dan ideologis agar visioner. Pada gilirannya, semua itu akan membuatnya sadar perihal konsekuensi praktis kehidupan individual dan sosialnya serta siap menanggung pelbagai risikonya. Ringkasnya, dalam beragama, membekali diri dengan logika akidah lalu logika fikih, merupakan suatu kemestian.