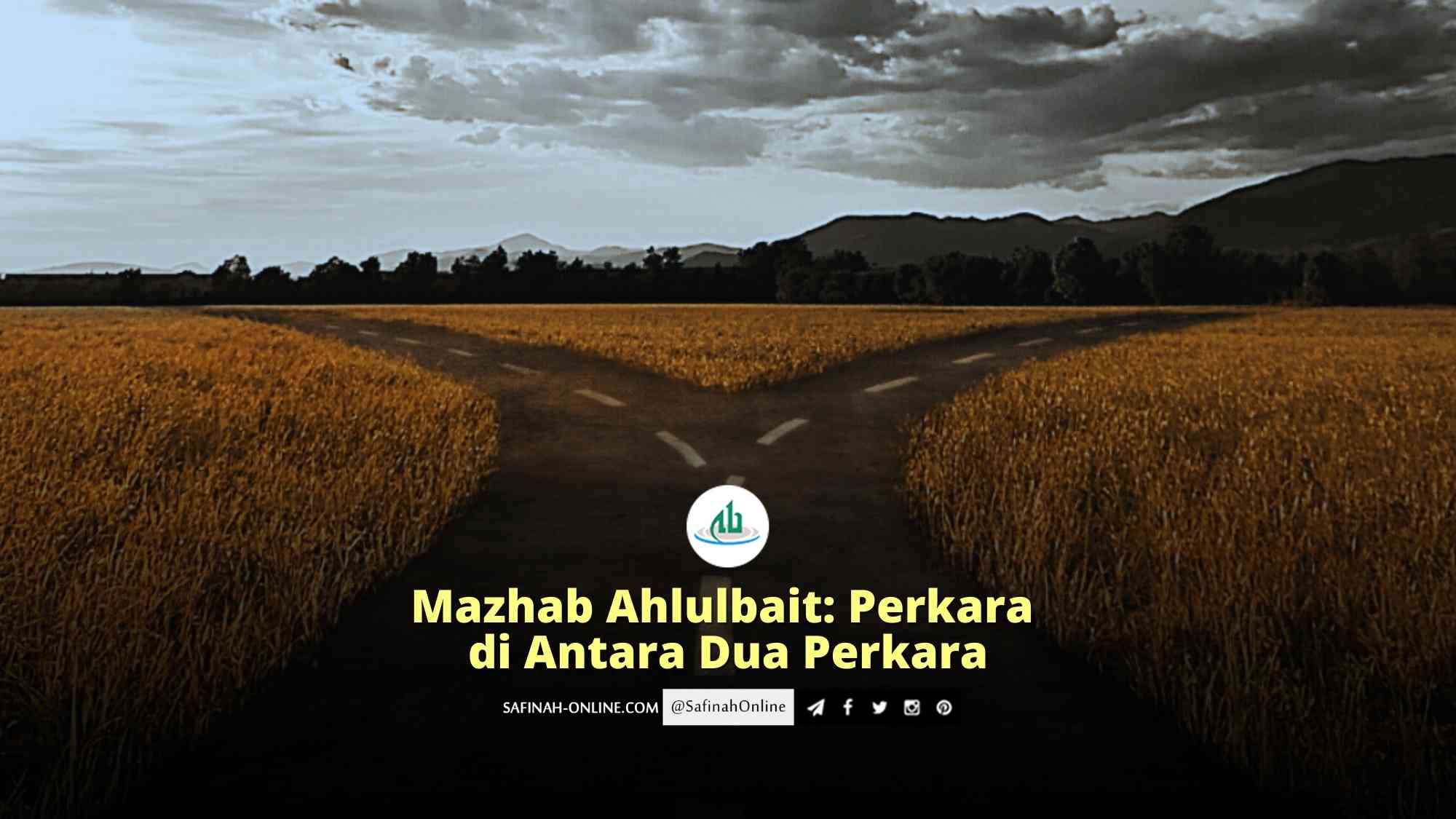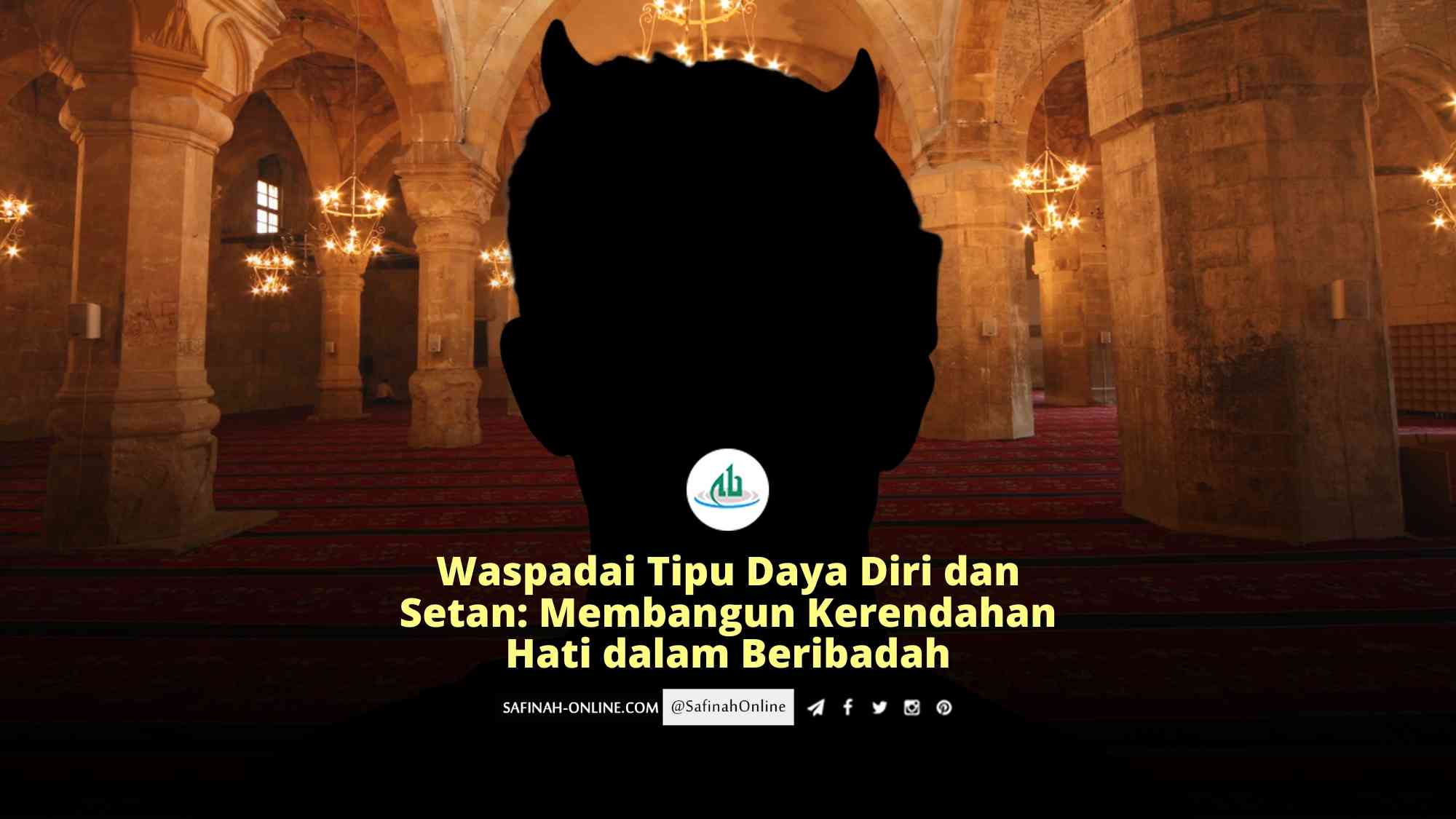Mazhab Al-Qur’an adalah jelas berbeda dari mazhab Jabariyah dan Muktazilah sekaitan dengan masalah sensitif dalam hidup manusia. Al-Qur’an menawarkan mazhab ketiga, yang dikenal sebagai “Al-Amru Baina Al-Amrain” (perkara di antara dua perkara).
Mazhab ini berada di tengah-tengah antara dua mazhab ekstrem, dan Ahlulbait adalah pemimpinnya. Mereka adalah tokoh utama mazhab Al-Qur’an yang rasional ini dan pertama kali memperkenalkannya kepada manusia. Namun, meskipun konsep ini moderat, pada awal Islam, tidak banyak dibahas dalam diskusi ulama Muslim.
Faktor yang Mengalihkan Ulama Muslim dari Konsep “Al Amru Baina Al Amrain”
Penyebab perubahan fokus para ulama Muslim dari konsep “Al Amru Baina Al Amrain” adalah kaum Jabariyah. Mereka ingin melepaskan tanggung jawab perbuatan zalim manusia kepada Allah dan menyucikan-Nya dari segala kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Ini menyebabkan konfrontasi dengan pengikut Muktazilah, yang meyakini bahwa semua tindakan harus diatribusikan kepada manusia, bukan Allah.
Kaum Muktazilah berpegang pada doktrin kemandirian manusia dalam berkehendak, menolak gagasan bahwa Allah memiliki kehendak dan kuasa atas manusia dalam berkehendak dan bertindak. Mereka berpendapat bahwa Allah hanya menciptakan manusia dan memberi mereka kemampuan berkehendak, dan kemudian memberi tanggung jawab kepada manusia dalam berkehendak.
Baca: Manusia dan Taklifnya
Menurut pandangan mereka, proses penciptaan manusia tidak bertentangan dengan kemandirian manusia dalam berkehendak. Mereka berargumen bahwa setiap entitas yang mungkin memerlukan Allah hanya pada tahap permulaan. Jika entitas tersebut sudah ada, maka entitas tersebut bertindak mandiri, terlepas dari Allah.
Mereka percaya bahwa menolak kemandirian manusia dalam berkehendak akan mengarah pada menyalahkan Allah atas tindakan manusia, yang juga merupakan kesalahan yang dilakukan oleh kaum Asy’ariyah. Namun, menurut pandangan mereka, jika manusia berkehendak mandiri, tidak ada yang bisa menyalahkan tindakan manusia kepada Allah.
Kebebasan Berkehendak vs Kemandirian
Pentingnya memahami bahwa kebebasan berkehendak tidak sama dengan kemandirian. Kebebasan berkehendak mengacu pada kemampuan manusia untuk memilih, sementara kemandirian berarti tidak ada ketergantungan mutlak pada manusia dalam tindakan mereka. Ini tidak membuat kebebasan berkehendak menjadi identik dengan kemandirian.
Dalam konteks ini, tidak masalah jika tindakan manusia tergantung pada pilihan dan tindakan sebelumnya. Yang penting, kebebasan berkehendak adalah kemampuan untuk memilih antara pilihan yang ada.
Interpretasi Ulama Mazhab Ahlulbait terhadap Konsep Al Amru Baina Al Amrain
Sekarang, kita akan mencoba memahami bagaimana para ulama Ahlulbait mengatasi masalah ini dengan menggabungkan dua hal: pertama, keyakinan tentang keterkaitan Allah dalam kehendak dan tindakan manusia (sesuai Al-Qur’an); dan kedua, upaya untuk menjaga kesucian Allah dari kezaliman dan kejahatan. Kedua doktrin ini disebut dalam Al-Qur’an.
Al-Qur’an menegaskan bahwa manusia selalu membutuhkan Allah dalam semua aspek kehidupannya, dan Allah memiliki kekuasaan dan pengaruh yang berkelanjutan terhadap tindakan dan kehendak manusia. Sekarang, kita akan menjelaskan pandangan filsafat tentang masalah ini. Kaum Mufawwidhah meyakini bahwa setelah manusia ada, ia tidak lagi memerlukan penyebabnya dalam tindakan dan kehendaknya secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa setelah menciptakan manusia, Allah tidak lagi terlibat dalam tindakan dan kehendak manusia.
Namun, pandangan ini keliru karena bertentangan dengan bukti rasional yang menunjukkan bahwa akibat selalu bergantung pada penyebabnya, baik pada tahap kebermulaannya maupun keberlanjutannya. Jika penyebab menghilang, akibatnya juga menghilang. Akibat selalu bergantung pada penyebab, dan jika hubungan ini terputus, akibat akan menghilang.
Pendapat bahwa akibat tetap ada meskipun penyebabnya sudah hilang adalah pandangan yang salah dan tidak sesuai dengan hukum sebab-akibat. Hubungan sebab-akibat adalah dasar bagi eksistensi akibat, dan ketika hubungan ini terputus, akibatnya juga lenyap. Kami tidak akan mendalami masalah ini lebih jauh di sini, tetapi bagi yang tertarik, ada banyak kajian filsafat yang menguraikan masalah ini dari sudut pandang rasional.
Beberapa Model Penafsiran Ulama Ahlulbait terhadap Konsep Al Amru Baina Al Amrain
Setelah melihat keterangan sebelumnya, tidak ada lagi keraguan mengenai penolakan doktrin tafwidh oleh Muktazilah, baik dari perspektif Al-Qur’an maupun akal. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana konsep Al Amru baina Al Amrain, yang menolak determinisme dalam tindakan manusia, pada saat yang sama menolak doktrin kemandirian manusia dan pengalihan segala urusan kepada-Nya?
Penolakan terhadap kemandirian manusia dan konsep pengalihan urusan mengarah pada keyakinan bahwa segala bentuk kezaliman dan keburukan harus diatribusikan kepada Allah. Ini adalah konsekuensi yang ingin dihindari oleh Muktazilah. Al-Qur’an sangat menekankan konsep Al Amru baina Al Amrain, sehingga bagi para ulama bukanlah pengakuan terhadap konsep ini yang menjadi masalah, melainkan bagaimana konsep ini, yang diumumkan oleh Ahlulbait, dapat diinterpretasikan sehingga tidak menyalahkan Allah atas segala bentuk kezaliman, dan sekaligus menghindari kesalahan konsep kemusyrikan.
Para ulama Ahlulbait berusaha untuk mencari petunjuk dalam teks-teks otoritatif Ahlulbait dalam menafsirkan dan menjelaskan konsep ini. Ada beberapa model penafsiran, tetapi yang paling terkenal dan jelas adalah sebagai berikut:
Penjelasan dan Syarah Konsep Al Amru Baina Al Amrain
Penafsiran yang paling dikenal dari para ulama Ahlulbait didasarkan pada prinsip bahwa hubungan antara semua eksistensi dengan Allah berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan. Manusia dalam alam semesta ini bergantung kepada Allah dalam segala kekurangan dan kebutuhannya, dan berinteraksi dengan-Nya melalui proses emanasi dan penciptaan.
Proses emanasi ini berlangsung terus-menerus dan tidak terputus. Jika saja proses emanasi ini terhenti sesaat dari manusia, maka eksistensi manusia dan segala yang dimilikinya seperti harta, kehendak, tindakan, kemampuan, dan lainnya akan berakhir. Meskipun manusia bergantung pada emanasi ini, tetapi manusia tetap yang berkehendak dan bertindak.
Baca: Analisa Hadis Islam Terpecah dalam 73 Golongan
Sebagai contoh, jika Allah menghentikan emanasi eksistensial dan penyediaan daya, akal, kesadaran, pengetahuan, kemampuan, dan kehendak manusia, maka manusia tidak akan mampu untuk berkehendak atau melakukan sesuatu. Namun, pada saat ini, manusialah yang memiliki kehendak, berkeinginan, dan bertindak. Oleh karena itu, tidak benar untuk mengatribusikan tindakan manusia kepada selain dirinya sendiri; manusia bertanggung jawab atas semua perbuatannya.
Terkait dengan emanasi Ilahi, Allah Swt telah menyatakan:
“Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka.” (QS Al Baqarah: 20)
Allah Swt juga berfirman, “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya.” (QS Al-An’am: 137)
Contoh yang baik untuk menjelaskan hal ini adalah dengan mengamati seorang insinyur yang bertanggung jawab atas pusat pembangkit tenaga listrik yang memasok listrik ke sebuah rumah. Insinyur ini bertanggung jawab untuk menjaga agar aliran listrik terus mengalir agar penghuni rumah dapat menggunakannya. Jika penghuni rumah ini dengan sengaja menggunakan listrik untuk melakukan tindakan yang berbahaya, seperti bunuh diri dengan menyalurkan listrik ke tubuhnya atau membahayakan orang lain dengan listrik, maka semua tindakan tersebut tidak dapat disalahkan pada siapa pun kecuali penghuni rumah itu sendiri. Meskipun insinyur bertanggung jawab atas pasokan listrik, ia tidak dapat dianggap sebagai pelaku tindakan tersebut.
Dalam contoh ini, satu-satunya individu yang dapat disalahkan adalah penghuni rumah, dan ia bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Tidak ada dasar untuk mengklaim bahwa insinyur yang memutus aliran listrik atau gagal menjaga pasokan listrik harus bertanggung jawab atas tindakan bunuh diri penghuni rumah atau tindakan berbahaya lainnya. Perumpamaan seperti ini adalah perumpamaan yang paling tepat dalam konteks ini dari segi ilmiah dan perincian.
*Disarikan dari buku Keadilan Tuhan, Determinisme Sejarah, dan Mendirian Tindakan Manusia – Markaz ar- Risalah