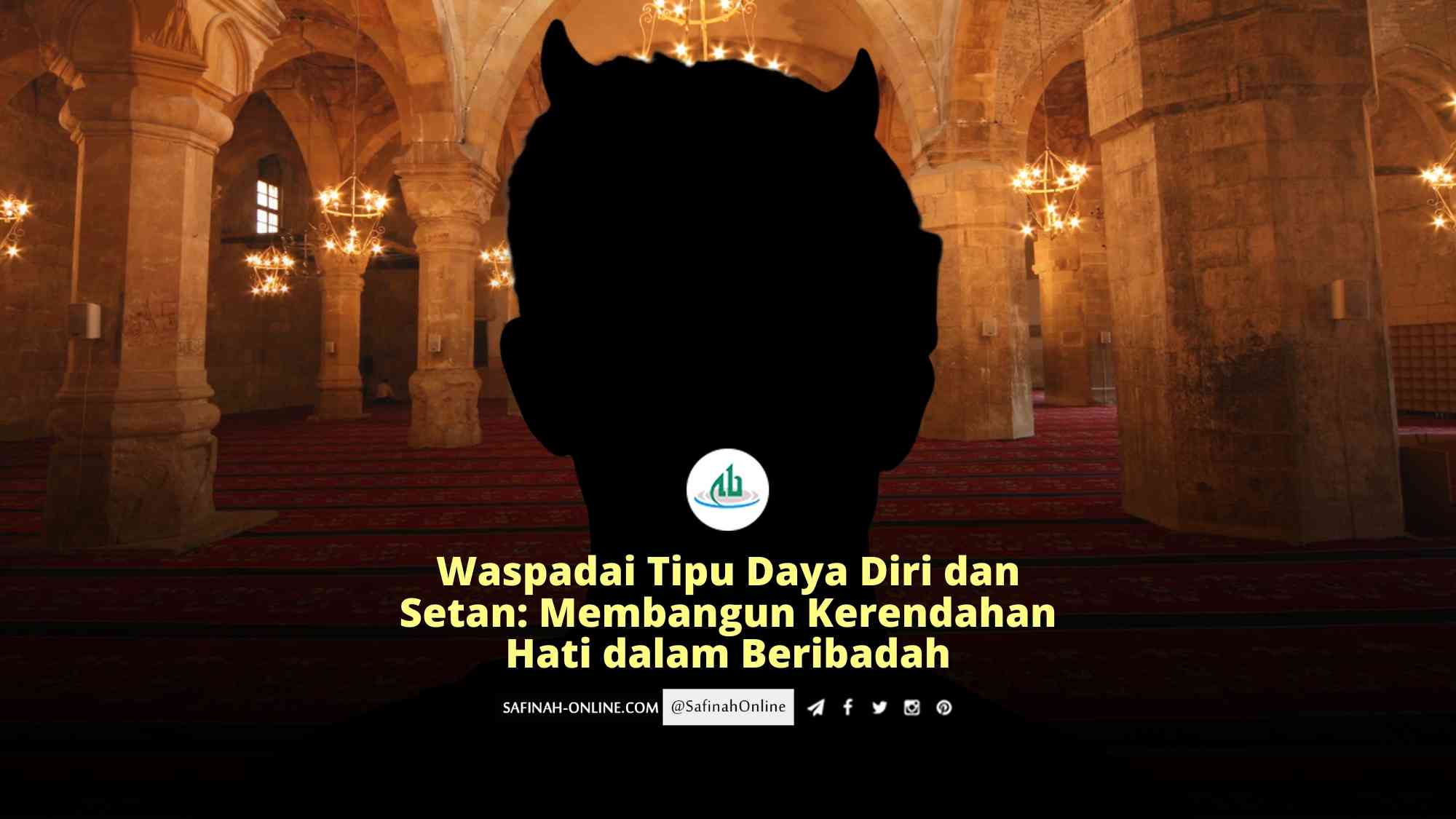Oleh: Ustaz Musa Kazhim Alhabsyi
Dalam sejarah Islam, masalah imamah telah memicu konflik yang berkepanjangan. Asy-Syahrastani, pengarang al-Milal wa an-Nihal, menyatakan bahwa tidak ada faktor pertikaian di kalangan umat Islam yang lebih besar daripada masalah imamah. Mazhab Syiah dan Ahlusunah berbeda pandangan dalam definisi imamah, kriteria seorang imam, metode penentuan imam, legitimasi imam, individu- individu imam, dan lain sebagainya. Secara umum, mazhab Ahlusunah memandang imamah identik dengan khilafah dan membatasi cakupannya pada ranah politik, sementara Syiah memberikan peran yang jauh lebih besar.
Menurut Ahlusunah, seorang “imam” pertama-tama dan terutama adalah seorang pemimpin politik yang bertugas memerintah dan mengatur tatanan sosial-politik. Karena itu, logis kiranya bilamana pemimpin politik yang biasa disebut dengan “khalifah” ini tidak perlu terlalu tinggi dalam hal keilmuan atau ketakwaan, melainkan cukup memiliki sifat adil (‘adalah). Sebagai pemimpin politik suatu masyarakat sudah sepatutnya imam ini dipilih secara sosial-politik ini ditegaskan dalam firman Allah yang berbunyi: “Dan urusan mereka (diputuskan) melalui musyawarah di antara mereka.” (QS. asy-Syura: 38)
Singkat kata, karena imam tidak lebih daripada khalifah yang dipahami sebagai “pemegang kekuasaan politik”, maka syarat “adil” dan “dipilih secara musyawarah” sudah cukup untuk membuat siapa saja mencalonkan diri sebagai imam. Benar saja, selain dari empat khalifah pertama yang digelari dengan “al-Khulafa’ ar-Rasyidun”, umat Islam hampir tidak pernah lagi mempunyai pemimpin atau khalifah yang adil dan bijak.
Lembaran-lembaran hitam mengisi sejarah Islam justru karena kezaliman dan kekejian penguasa-penguasa yang oleh sebagian umat Islam disebut sebagai khalifah atau amirul mukminin. Yazid yang terkenal zalim dan bengis dapat berkuasa di tengah-tengah umat Islam. Pada masa kekuasaannya, bermacam-macam kejadian tragis terjadi. Puncaknya, Yazid memaksa Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunda Nabi Muhammad Saw, untuk tunduk dan berbaiat (melakukan sumpah setia) kepadanya. Manakala Imam Husain menolak paksaan baiat itu, belau dan sebagian besar anggota keluarga dan sahabatnya dibantai secara biadab oleh kaki tangan Yazid, di padang Karbala pada tanggal 10 Muharam tahun 61 H.
Berbeda dengan itu, menurut mazhab Syiah, imamah memiliki dimensi spiritual yang jauh lebih penting dibandingkan dengan dimensi politiknya. Dimensi spiritual ini adalah dasar, sedangkan dimensi politik adalah cabangnya. Dengan kata lain, seorang imam menjadi imam, pertama dan terutama karena maqam (kedudukan) spiritualnya yang tinggi di sisi Allah Swt dan kualitas-kualitas jiwanya yang sempurna. Karena itu, untuk mengetahui imam dalam pengertian ini, mau tidak mau, kita mesti mengacu kepada nas dan petunjuk Allah. Legitimasi seorang imam juga tidak diperoleh lewat musyawarah atau baiat. Imam dalam arti yang demikian menjadi imam bukan karena pengakuan atau kesepakatan orang, melainkan karena kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Swt.
Baca: Perbedaan antara Nubuwah, Imamah, dan Risalah
Dengan demikian, persoalan ini tidak bisa dikaitkan dengan musyawarah atau kesepakatan publik. Para nabi dan rasul tidak mendapatkan kedudukan mereka melalui musyawarah atau pemungutan suara, melainkan melalui penunjukan dari Allah dan ketinggian spiritualnya. Jadi, wilayah imamah secara primer bukanlah wilayah publik, dimana kesepakatan dan pengakuan memiliki peran esensial, melainkan termasuk dalam wilayah agama yang meliputi wilayah publik.
Dalam perspektif seperti ini, imam bukan hanya khalifah yang hanya berperan menggantikan tampuk kekuasaan politik setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw, melainkan juga seperti tercantum dalam pelbagai hadis Nabi, mereka adalah para pemberi syafaat, wasilah menuju Allah, pendamping Al-Qur’an, penjaga agama, pintu menuju Allah, pilar kehidupan di bumi, penopang kebenaran, dan tidak dapat dibandingkan dengan manusia biasa (Lebih jauh, silahkan rujuk karya Muhammad ar-Raysyahri – Ahlulbait fi al-Kitab wa as-Sunnah, Mu’assasah Dar al-Hadits). Mereka ini adalah wali-wali Allah yang berperan sebagai pintu-pintu dan perantara-perantara menuju Allah. Itulah sebabnya, konsep tawasul dalam Syiah merupakan ajaran yang fundamental.
Menurut pandangan Syiah, hubungan antara nubuwah dan imamah bersifat irisan (intersection). Yakni, sebagian nabi sekaligus juga imam, tapi tidak semua imam menerima wahyu layaknya seorang nabi. Nubuwah berakhir dengan baginda Muhammad Saw, tetapi imamah tidak berakhir dengan beliau Saw. Puluhan hadis yang berkaitan dengan kedudukan Ali bin Abi Thalib as. Sebagai pengganti (washi) Nabi Muhammad Saw merujuk pada fungsi imamah yang terus berlanjut, meskipun nubuwah dalam pengertian turunnya wahyu berakhir dengan Nabi Muhammad Saw.
Salah satu nas yang secara jelas berbicara mengenai imamah terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 124: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: ‘Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.’ Ibrahim berkata: ‘(Dan saya mohon juga) dari keturunanku.’ Allah berfirman: ‘Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim.’”
Menurut para mufasir, Nabi Ibrahim as. ditetapkan Allah sebagai imam setelah beliau menjadi nabi, sehingga status imamah dan nubuwah bergabung pada diri Ibrahim as. (Sayid Kamal Haydari, Bahtsun Haul al-Imamah. Dar ash-Shadiqin, hal. 93)
Dalam ayat di atas, Al-Qur’an menyebutkan bahwa imamah Nabi Ibrahim as. diperoleh setelah beliau melewati pelbagai cobaan dan ujian. Selain menunjukkan ketinggian status imamah, ayat tersebut juga menunjukkan bahwa seseorang tidak menjadi imam kecuali dengan bersabar menghadapi pelbagai ujian. Dan masalah kesabaran menghadapi ujian ini ditegaskan juga dalam ayat lain: “Dan Kami jadikan di antara mereka (Bani Israil) imam-imam yang memberikan petunjuk dengan perintah ketika mereka bersabar. Dan mereka adalah orang-orang yang meyakini ayat-ayat Kami.” (QS. as-Sajadah: 24)
Baca: Tujuan Perjuangan Politik Para Imam Maksum a.s.
Dalam ayat yang disebut belakangan, selain masalah kesabaran, AI-Qur’an juga menyebutkan keyakinan sebagai syarat lain seseorang mencapai maqam imamah. Masalah keyakinan ini secara khusus pernah diminta oleh Nabi Ibrahim as. dalam upayanya mencapai maqam imamah. Allah Swt berfirman: “Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: ‘Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati.’ Allah berfirman: ‘Apakah kamu belum percaya?’. Ibrahim menjawab: ‘Aku sudah percaya, namun agar semakin tenteram hatiku.’” (QS. al-Baqarah: 260)
Keinginan mendapat ketentraman batin ini kemudian diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim as. Allah SWT berfirman: “Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan di bumi, agar dia termasuk dalam golongan orang-orang yang yakin.” (QS. al-An ‘am: 75)
Melalui kualitas kesabaran dan keyakinan itulah seorang imam memperoleh kemaksuman (‘ishmah), kesucian dan penyucian dari Allah (QS. al-Ahzab: 33). Kemaksuman adalah keadaan terbebas dari segala dosa dan kezaliman dalam pelbagai tingkatannya seperti tersiratkan dalam surat al-Baqarah ayat 124: “… janji-Ku tidak mencakup orang-orang yang zalim.”
Tentu saja, kemaksuman ini tidak diperoleh oleh sembarang orang lewat sembarang cara. Kemaksuman diperoleh lewat kesabaran seorang hamba dalam menyongsong pelbagai ujian dalam menuju Allah Swt dan melalui keyakinannya yang mendalam. Sejujurnya, apabila imam itu kita pahami hanya sebagai seorang pemimpin atau penguasa politik, maka akidah Syiah mengenai kemaksuman para imam ini jelas berlebih-lebihan. Dengan mudah orang akan menunjukkan bukti-bukti rasional maupun pragmatis, bahwa seorang penguasa atau kepala pemerintahan tidak harus maksum, melainkan cukuplah baginya sifat adil. Namun, masalahnya berbeda bilamana imam ini kita pahami sebagaimana yang termuat dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi saw yang menuturkan mengenai imam dan imamah.